Jika normalnya seorang bayi lahir akan menangis dan beberapa menit kemudian tembuninya keluar, maka tidak dengan Kakek. Setidaknya begitu yang kudengar dari cerita turun-temurun keluarga yang kerap diulang Ibu padaku.
“Kakek lahir, dan langsung bernyanyi bersama gitarnya.”
Dulu, aku selalu mencibir dan mencemooh cerita itu, sampai kemudian kakek tinggal bersama kami, tepatnya dua bulan yang lalu. Setelah kematian Nenek, usianya yang sudah lanjut tak mengizinkannya lagi untuk tinggal sendiri (bagaimana Nenek tetap waras sampai ia dikebumikan sedangkan Kakek malah sebaliknya tetap merupakan misteri bagiku). Sebagai anak bungsu yang baru menginjak remaja, aku dianggap masih tak perlu kamar sendiri sebagai ruang privasi, sehingga harus rela berbagi.
“Yang penting Kakek nggak ngelindur, ya…” aku bersungut-sungut.
Semakin tua Kakek justru semakin seperti anak kecil. Hanya sesekali kujumpai ia mengatakan sesuatu yang tak mencerminkan kepikunan. Sisanya, ia akan menghabiskan hari memetik gitar kesayangannya yang senarnya tinggal satu.
“Ini sisa umurku,” jelasnya suatu sore, ketika dilihatnya aku memasang tampang iba pada gitarnya. Ia kemudian melanjutkan memetik sambil sesekali berucap. Kalimatnya pendek-pendek. Terputus-putus. Ditingkahi petikan. “Pertama putus usia duapuluh. Lalu tiga tujuh. Lalu entah usia berapa. Yang terakhir waktu nenekmu meninggal.”
Sudah dua bulan ini pula malam hari yang kulalui terasa begitu menyiksa. Bagaimana tidak, Kakek bisa memetik gitarnya sampai lewat tengah malam. Telah kusampaikan keluhanku pada Ibu namun ia hanya menggeleng sambil menggumamkan sesuatu yang tak bisa kumengerti hingga akhirnya aku menyerah.
“Setiap manusia lahir dengan gitarnya,” Kakek membuka suara untuk pertama kalinya malam ini. Aku melirik jam dinding. Setengah sebelas. “Gitarmu di mana?”
Aku terbiasa mendiamkan Kakek, karena biasanya ia juga tak butuh jawaban. Tapi saat kupalingkan wajah padanya, ia sedang menatapku, seakan menunggu.
Aku menggeleng tak acuh, “Nggak punya.”
“Pasti disimpan ibumu. Ia tak mau kamu seperti ayahmu.”
Obrolan tentang ayah merupakan hal tabu di rumah. Darahku berdesir cepat saat mendengar kakek menyinggungnya. Baru aku membuka mulut untuk lebih lanjut bertanya, kakek sudah membalikkan badan memunggungiku.
Ayah seorang wartawan politik. Tabiatnya yang keras kerap membuatnya terlibat dalam kesulitan. Dari cerita yang secara sembunyi-sembunyi disampaikan kerabat padaku, Ibu sudah sering mengingatkan Ayah untuk berhati-hati dalam tulisannya namun hal itu justru membuat Ayah marah dan merasa tidak didukung.
Kemudian suatu pagi, Ayah pergi dan tak pernah kembali.
Aku baru berumur tiga tahun saat itu.
Satu-satunya ingatan samar tentang Ayah adalah bau kerah bajunya yang manis dan membuatku mengantuk. Ia biasa menggendongku sampai tertidur, kadang ia membiarkanku terlelap di sampingnya, ketika ia sedang mengetik dengan mesin ketik tuanya.
Suara mesin itu jauh lebih baik daripada gitar berdawai satu. Aku mengeluh dalam hati. Kulirik Kakek yang sedang tertidur pulas. Pelan kucoba untuk membangunkannya. Ia tak bereaksi saat kusentuh bahunya.
Sebuah pikiran usil melintas di benakku.
Kutarik pelan gitar yang dipeluknya. Seutas benang melilit benda itu dan tampaknya terikat erat pada tubuh Kakek. Keningku berkerut. Orang tua aneh, ia pasti tak mau gitarnya hilang.
Tak putus asa, kugunting benang pengikat gitar.
Kusurukkan benda itu jauh ke bawah tumpukan baju kotor.
Malam itu aku tertidur dengan lelap kembali.
—
Keesokan harinya aku bangun dengan kepala berdenyut. Samar kudengar isak tangis dan suara membaca Yasin. Ranjang di sebelahku kosong.
Setiap manusia lahir dengan gitarnya…
Maka kutuliskan kisah ini.

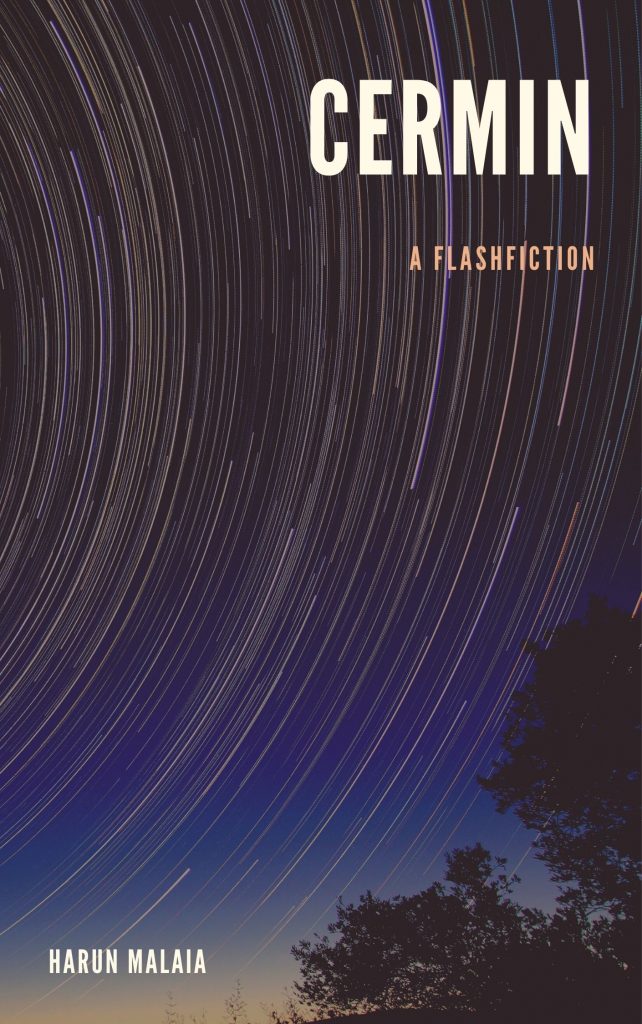
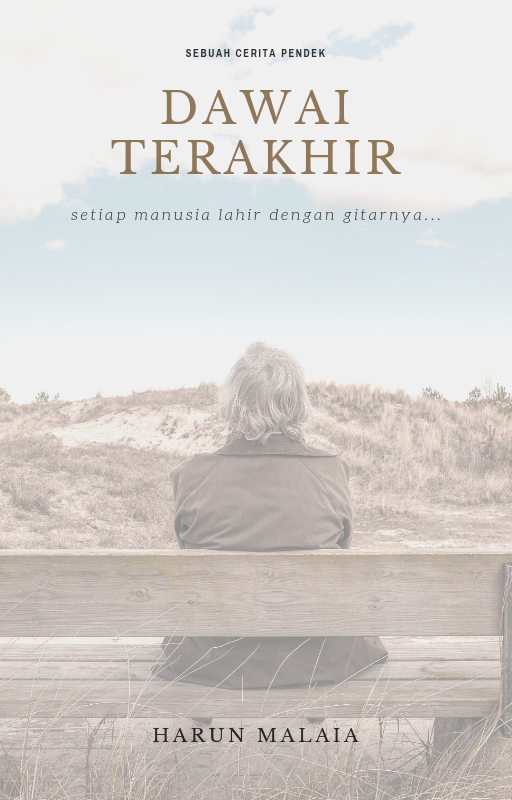
Tinggalkan Balasan