Matahari masih berada di atas kepala saat Madi menerobos semak-semak membentang yang memisahkan jalan setapak yang tadi ia lewati dengan hamparan sawah yang sedang ia tuju. Sebenarnya jika ia terus saja berjalan mengikuti jalan setapak, ia pada akhirnya juga akan tiba ke sawahnya. Tapi ia memilih melintasi semak-semak perdu ini. Paling tidak ia akan tiba lebih cepat daripada seharusnya. Perutnya sudah berbunyi sejak lama. Pagi tadi ia memang terburu-buru sehingga tak sempat mengisi perut. Ia hanya meminum setengah gelas teh hangat. Itupun ia langsung diteriaki oleh ibunya karena meminum teh miliknya.
Namun betapa kecewanya ia saat melihat dangau kosong. Seakan tak percaya, ia bergegas mendekat dan memeriksa. Tapi memang tidak ada siapa pun di sana. Dengan lesu ia meletakkan sepatu yang sedari tadi ia jinjing — jalanan yang tadi ia lewati tidak hanya berhias semak berduri, tapi juga lumpur yang lengket. Lumpur itu meninggalkan bekas sampai hampir mencapai lutut. Madi menggaruknya. Kini ia bukan hanya lapar. Tapi juga gatal.
Tiba-tiba ia teringat, ia pernah memeram buah mangga. Maka ia bangkit dan memeriksa bakul kecil di sudut dangau. Untunglah, ia masih beruntung. Tak hanya mangga yang ia dapatkan. Ternyata ibunya juga memeram tiga buah pisang tanduk yang kini sudah berwarna kuning. Ia bisa mencium baunya. Mangganya tidak terlalu matang. Sepertinya besok akan pas matangnya. Tapi perutnya terlalu lapar untuk bisa menunggu besok. Maka Madi memutuskan akan memakannya demi mengganjal perutnya yang sudah benar-benar kosong.
Saat menghabiskan pisangnya yang kedua ia berpikir tentang bagaimanakah reaksi ibunya jika tahu ia telah memakan pisangnya. Sedang meminum setengah gelas tehnya saja ia sudah diteriaki seperti seorang maling. Memikirkan itu Madi berhenti mengunyah, pisangnya tinggal setengah.
Ia lalu membuka tasnya. Mengeluarkan sebuah bingkisan. Hadiah. Ia mendapat rangking dua di kelasnya. Ia mendapat hadiah untuk itu. Sepertinya buku. Apalagi? Madi mencoba merabanya dari sudut ke sudut. Sepertinya memang buku.
Paling tidak Didi tidak perlu lagi membeli buku. Adiknya itu sekarang kelas dua SD. Jika tadi ia naik kelas berarti sekarang ia kelas tiga. Madi memberengut, pasti bukunya ini akan banyak diminta untuk Didi. Tapi kemudian ia tersenyum, ia berniat menggoda Didi jika pulang nanti. Ia akan berpura-pura pelit. Biar Didi menangis dulu. Pasti seru. Biasanya Didi jika menangis suka sampai berguling-guling. Diam-diam Madi menertawakan khayalannya.
Sekali lagi diperhatikannya hadiah di tangannya itu. Juara dua. Lalu diambilnya buku raportnya. Memang juara dua. Ia terpaut satu angka dengan Hamid, sang pemuncak di kelasnya. Mulut Madi mengerucut, meneliti nilai-nilai yang tertera. Tadi ia sudah memeriksanya. Sekarang ia ingin menikmatinya. Oh ya. Bahasa Inggris. Ia hanya mendapat angka delapan. Sedang Hamid sembilan. Tentu saja ia kalah, melihat kamus Hamid saja sudah akan memastikan nilai Hamid. Sedang ia sendiri, punya sebuah kamus kecil yang justru banyak tidak memuat kata-kata penting. Itupun pinjaman.
Kaki Madi kini berwarna coklat keputihan. Lumpur tadi sudah mengeras. Madi menggesek-gesekkannya ke tiang dangau, membuatnya terkikis. Paling tidak kini kakinya tidak terasa terlalu keras. Ia menggoyang-goyangkannya, sepertinya tadi kakinya tergores, kini gantian lalat yang mengerubungi kakinya.
Perutnya kini tak lagi terlalu keroncongan. Tapi kini ia malah memikirkan nilai raportnya. Madi membuka-buka lembarannya dari awal. Juara dua. Juara dua. Juara dua lagi. Yang ini juga juara dua. Selalu juara dua. Mata Madi menerawang. Juara satunya selalu Hamid. Ya. Hamid tak pernah tidak juara satu. Mereka sudah satu kelas sejak SD. Dan selama itu — sampai sekarang kelas dua SMP, ia selalu juara dua dan Hamid yang memegang juara satu.
Hamid. Abdul Hamid. Madi langsung terbayang wajah temannya itu. Ya, meski mereka bersaing, tapi mereka tetap berteman. Sebenarnya Madi agak segan berteman dengan Hamid. Ia anak Haji Mahmud, orang terkaya di desa.
Kening Madi tiba-tiba berkerut. Iya ya. Hamid anak orang kaya. Pintar. Selalu juara satu. Anaknya ramah. Bersih — Madi memandangi kakinya yang dikerubungi lalat. Wajahnya juga tampan. Hamid ketua OSIS…
Wah! Kening Madi makin berkerut. Makin dipikir-pikir, ternyata Hamid begitu lebih. Ia sendiri? Hanya juara dua. Anak orang miskin. Harus ikut bekerja mengambil upah membersihkan sawah milik tetangganya yang lumayan berada jika musim tanam sawah. Rumahnya bahkan sering bocor jika hujan turun terlalu deras.
Madi lalu meneliti kembali nilai-nilainya. Sebenarnya ia berharap menemukan ketidakcocokan. Maksudnya nilainya lebih dari nilai Hamid. Tapi sepertinya Bu Tini menghitung dengan kalkulator. Tidak ada yang salah. Matematika…! Oh ya. Ia yakin saat ujian nilainya lebih tinggi daripada nilai Hamid, sebab mereka saling mencocokkan jawaban setelah selesai ujian. Tapi kenapa nilai mereka jadi sama? Hamid juga dapat sembilan. Iya ya. Kenapa malah bisa sama?
Tiba-tiba Madi menepuk kepalanya sendiri. Tertawa keras. Bodohnya ia. Bukankah nilai raport juga diambil dari nilai harian? Pantas saja jika mereka berdua pada akhirnya mendapat nilai yang sama. Selama ini nilai harian Hamid selalu baik. Madi manggut-manggut sendirian.
Tapi kenapa ia tak pernah bisa mengungguli Hamid?
Perut Madi kembali berbunyi. Ia lalu menghabiskan sisa pisangnya tadi. Di sela keasyikannya mengunyah ia berusaha mengingat-ingat kapan ia pernah mengalahkan Hamid. Oh ya. Pernah. Saat pelajaran Olahraga. Ia menjadi yang tercepat dalam nilai lari 100 meter. Sedang Hamid masuk lima besar saja tidak. Hamid hanya urutan tujuh. Tapi di raport, Hamid tetap mendapat sembilan. Wah. Madi mengeluh kecewa. Kenapa nilai mereka bisa sama lagi?
Madi memasukkan raportnya kembali ke dalam tasnya. Tangannya menyentuh sesuatu. Permen. Oh iya. Tadi Asti ulang tahun. Ia membagi-bagikan permen bagi teman sekelas. Tadi sebenarnya lima. Kini hanya tinggal dua. Madi ingat telah memakan tiga lagi saat berjalan pulang tadi.
Saat berniat membuka sebuah permen lagi, Madi teringat Didi. Didi sangat suka permen ini. Madi membatalkan niatnya. Didi itu gemuk. Pasti tidak mau diberi satu. Madi memutuskan menyimpan dua sisa permennya untuk Didi. Oh ya, begini saja. Jika nanti Didi menangis tak diberi buku, baru ia akan memberikan permen sebagai ganti. Wah, pasti seru. Madi tersenyum-senyum sendiri.
Asti. Kini Madi memikirkan Asti. Sudah lama sebenarnya ia naksir Asti. Ia tidak ingat kapan persisnya. Yang pasti sudah lama. Ia ingat betapa senangnya ia saat diberi permen. Langsung dari Asti. Apalagi ia mendapat yang berbungkus pink. Sebenarnya ada juga temannya yang lain mendapat bungkus pink. Tapi rasanya berbeda saja. Madi diam-diam tersenyum malu. Tersipu. Digoyangkannya kakinya. Mengusir lalat. Sekarang ternyata juga ada agas. Kakinya makin gatal.
Tapi kabar burung yang beredar banyak menyebutkan kalau Asti justru menaruh hati pada Hamid. Mereka sering terlihat bersama. Rumah mereka berdekatan. Lho? Kenapa Hamid lagi? Madi menggaruk kepalanya dengan gusar. Ia memang melihat Asti mengucapkan selamat pada Hamid saat pembagian raport. Tapi… kenapa Hamid lagi? Masa kali ini ia juga harus kalah?
Seekor nyamuk menggigit kaki Madi yang memang tepat sebagai sasaran empuk. Madi memukulnya sekuat tenaga. Membuat nyamuk itu langsung lenyap, menyatu dengan lumpur kering yang menempel di kakinya. Melihat itu Madi langsung terbahak. Ia tak menyangka akan memukul sekeras itu. Mungkin ia terbawa perasaannya tadi. Bukankah tadi ia sedang jengkel pada Hamid?
Ah. Madi tiba-tiba kembali tersenyum. Buat apa ia susah-susah memikirkan perasaan orang lain? Bukankah Asti memiliki hak untuk menyukai siapa saja. Jika memang Hamid yang ia sukai, paling ia akan sedikit sedih, sebab berarti ia kalah untuk kesekian kali. Iya ya. Kenapa ia kalah terus. Kapan menangnya? Madi kembali menggaruk kepalanya. Kali ini karena memang kepalanya sedang gatal.
Suara kecipak air membuyarkan lamunan Madi. Ia menoleh mencoba memastikan apa yang berbunyi tadi. Lagi-lagi terdengar bunyi kecipak air. Kali ini Madi bisa melihat jelas sumber bunyinya. Perlahan bibir Madi membentuk senyuman.
Sepertinya ada ikan yang terjebak dalam lumpur sawah. Pasti terbawa air pasang beberapa hari yang lalu, pikir Madi. Ia melepas seragamnya. Menyampirkannya pada dinding dangau. Lalu mendekati ikan yang berkecipak tadi. Benar saja. Ada tiga ekor lele. Mata Madi langsung berbinar. Benar-benar lumayan. Pasti enak kalau dibikin sambal goreng.
Maka Madi pun terjun menangkap lele itu. Ternyata susah juga, mereka tak begitu saja mau menyerah. Padahal sudah sekering ini.
Wah, ternyata lebih dari tiga ekor! Empat! Eh, enam!! Di sana ada dua ekor lagi. Madi berteriak kegirangan. Matahari kini tak lagi berada di atas kepala. Lebih condong. Hampir rebah malah. Madi makin bersemangat. Perutnya masih keroncongan.
Matahari sudah hampir tenggelam saat Madi keluar dari lumpur. Benar-benar parah. Seluruh tubuhnya diliputi lumpur. Tapi ia senang karena berhasil menangkap tujuh ekor lele yang besar-besar. Sebenarnya ada banyak lagi. Entah bagaimana ada banyak lele. Madi memilih yang paling besar. Yang paling mudah ditangkap.
Terburu-buru Madi mandi di kolam. Ia ingat belum shalat Ashar. Maka ia segera naik dari kolam. Ikan-ikannya ia gantung dengan tali akar di tiang dangau yang mencuat. Segera ia memakai sarung. Seingatnya ada sarung di dalam bakul satunya. Untunglah ada. Tak sampai tiga menit Madi sudah selesai. Perutnya kembali keroncongan. Kini mulai terasa pedih malah. Heran. Bagaimana bisa ia belum makan dari pagi? Kenapa ia tadi tak langsung pulang saja? Iya ya. Madi memikirkan seandainya ia pulang tentu ia sudah kenyang sekarang. Tapi kemudian ia terbahak. Kalau tadi ia langsung pulang tentu ia tidak mendapat lele. Besar lagi. Tujuh ekor. Madi bernyanyi riang sepanjang jalan menuju rumahnya.
Hari sudah gelap saat Madi tiba di rumah. Ia sendiri heran. Ternyata ia terlalu lama saat di sawah. Menyadari itu, Madi bergegas masuk. Memanggil ibunya. Tadi ibunya tidak ke sawah. Lalu kemana? Iya ya. Kemana ibunya? Kenapa tadi ia tak memikirkan itu?
Madi meletakkan ikannya di dapur. Melongok kedalam kamar. Ah. Itu Didi. Didi sedang berbaring. Sepertinya tidur. Madi teringat ia punya permen. Juga buku. Maka ia mengambil tasnya. Mendekati Didi.
Tiba-tiba terdengar suara ibunya di luar. Madi tak jadi membangunkan Didi. Ia keluar kamar.
“Kau sudah pulang? Kemana saja seharian ini? Didi sakit. Demam. Badannya panas. Kau punya tabungan tidak?” ibunya menadahkan tangan.
Madi terdiam. Dadanya tiba-tiba terasa sesak. Entah kenapa. Pelan ia menggeleng. Lalu kembali masuk kamar. Mendekati Didi. Meraba keningnya. Bukan main. Panasnya tinggi.
Madi menggenggam hadiahnya kuat. Permen dari Asti tergeletak di samping bantal. Iya ya. Kenapa ia tak mendapat hadiah uang. Kalau saja buku bisa ditukar uang. Atau permen. Atau ikan. Kenapa tadi ia dapat ikan? Kenapa ia tak dapat uang?
“Besok kau libur tidak? Pak Hasan mengupahkan sawahnya. Mudah-mudahan besok kita dapat uang. Didi panas sekali.” Ibunya sudah berada di sampingnya, ikut duduk dan menggenggam tangan Didi. “Kau tahu penyakitnya? Di sekolah belajar penyakit tidak? Ibu takut sekali.”
Madi merasa hidungnya tiba-tiba beringus. Dadanya makin sesak. Pelan ia kembali menggeleng. Bangkit. Menuju dapur. Membuang ingusnya.
Ikan-ikan lelenya masih berontak di dalam ember. Mereka tak mudah menyerah ternyata. Padahal sekarang sudah benar-benar kering.

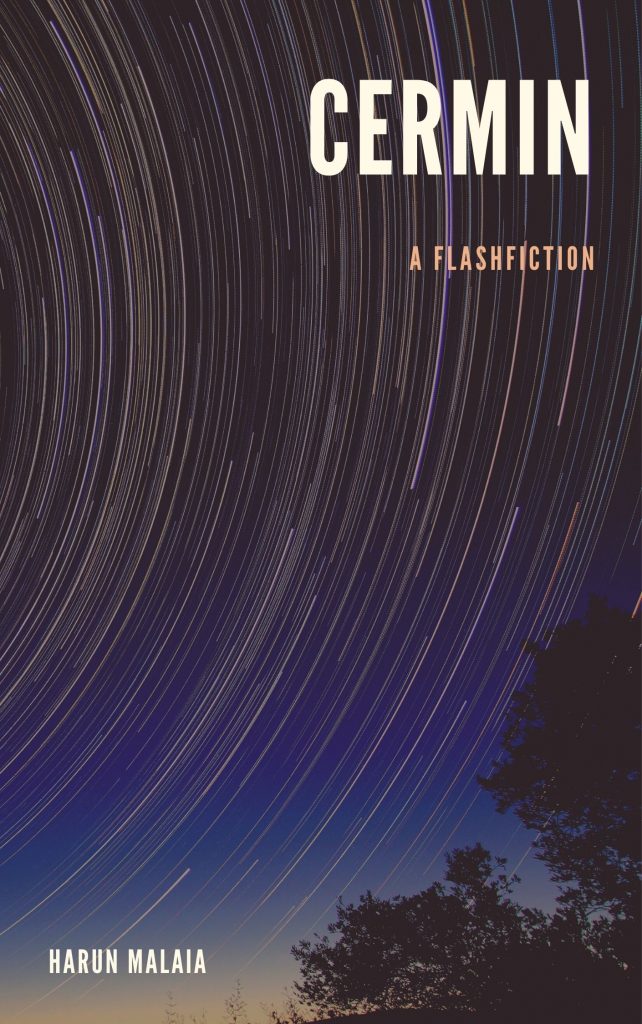

Tinggalkan Balasan