“Menurutmu, jika kita jatuh, apakah akan mati?”
Anwar menghentikan gerakannya menyuap sup—yang terlalu cair menurutku. Seperti biasa, dia hanya tersenyum, mengerti bahwa itu bukan pertanyaanku sebenarnya.
“Ada banyak teori tentang itu.”
“Tentang mati?”
“Kalau itu cuma satu.” Anwar menegakkan punggung, tiga jam—dan masih terus berlanjut—di perjalanan pasti membebaninya. “Maksudku sebelumnya: apa yang bisa terjadi pada kita—manusia, sesaat setelah pesawat ini jatuh.”
Aku yang tadinya bertanya sekadar membunuh bosan kini tertarik. Meski aku juga sebenarnya tertarik untuk membersihkan bekas sup yang menggaris di sudut kanan bibirnya.
“Ayahku—kau pasti ingat kalau dia seorang dosen; sama sepertimu—dan seorang yang sangat tertarik dengan dunia penerbangan jika boleh kutambahkan. Dia bisa menjelaskan ini lebih baik daripadaku.”
Sesaat pesawat mengalami turbulensi yang cukup kuat. Aku mencoba mengintip di jendela; hanya silau karena kami sedang menembus awan yang berkilau.
“Kita bisa saja jatuh sebentar lagi, dan ayahmu tak di sini, sayangnya,” gumamku.
Anwar tersedak dan tertawa. Atau sebaliknya.
Yang mana saja. Aku senang karena merasakan hangat yang menyeruak di dada saat mendengarnya tertawa. Atau melihatnya.
Yang mana saja.
Anwar tak sering tertawa, seingatku. Terutama sejak diagnosis kanker saluran empedu dia terima. Sulit untuk melihatnya tertawa lepas tanpa harus mengeluh sekali lagi tentang kondisi medisnya. Kuperhatikan sekali lagi saat Anwar menyekakan sudut tisu basah di sela-sela jarinya, berhati-hati memastikan sepotong kertas itu akan cukup untuk kedua tangannya.
Kisah tentang sakitnya Anwar akan sangat panjang, bahkan jauh lebih panjang daripada perjalanan di pesawat ini. Singkatnya, aku ingat Anwar menutupi rasa jengah yang nyata di air mukanya ketika aku dengan penuh penasaran membahasnya: aku mengakui bahwa gaya hidupku salah—dan kemudian itu menyebabkanku sakit. Aku mengutip kalimat lengkap Anwar di sana.
Tentu saja bukan itu penyebabnya. Gaya hidup yang mana? Aku dan Anwar berteman sejak kecil, berpisah saat masing-masing melanjutkan pendidikan dan bekerja. Menikah dengan pasangan masing-masing. Suamiku meninggal sementara Anwar bercerai. Lima tahun lalu kami bertemu dan Anwar belum dengan diagnosisnya. Jadi aku sendiri masih belum terbiasa dengan kondisi emosi Anwar. Ini semacam versi tambahan darinya. Anwar dan kanker. Penyakit dan Anwar.
Sekali lagi, bukan gaya hidup Anwar penyebabnya, aku yakin itu. Namun kita sebagai manusia (hampir selalu) butuh pelampiasan sebagai alasan untuk menyalahkan diri sendiri bukan?
Terlebih dengan penyakit yang muncul begitu perlahan hingga baru terdeteksi saat sudah terlambat.
“Belum,” tukas Anwar.
Aku tersentak, memalingkan wajah dari gumpalan awan-awan putih yang sepertinya lembut untuk dipegang.
Anwar mengerti kebingunganku, dia mengangkat pergelangan tangannya.
“Aku belum menyetel jam,” kembali diperhatikannya wajahku, sekilas senyum terbit di sudut bibirnya, yang menghilang begitu dia kembali membuka suara,”kau kerap melamun belakangan ini.”
Aku mengambil pergelangan tangannya, memperhatikan posisi jarum yang baru saja dia ubah. “Hanya selisih dua jam,” aku berlama-lama menggenggam tangannya.
Pernah beberapa kali aku memberitahu Anwar betapa jari-jari tangannya terasa besar saat menangkup di tanganku. Namun entah kenapa rasanya pas. Aku ingat kami bisa berjam-jam duduk di teras rumah berpegangan tangan. Anwar membaca buku dan aku mengintip sela-sela halamannya; lebih banyak membebani bahunya yang beraroma lavender—karena aku selalu menyeterika bajunya dengan parfum lavender. Sesekali Anwar terusik dan mengangkat bahunya seakan menyuruhku menjauh. Aku akan bersungut pergi lalu kembali membawa kudapan untuk menemaninya menghabiskan senja.
“Ada alasan kenapa manusia menyematkan cincin pada jari pasangannya,” jawabnya saat itu. Beberapa menit kemudian dia habiskan untuk menceritakan kebiasaan manusia saat mengklaim manusia lain sebagai pasangan hidup: memberi cincin, melukis tato, menusuk bagian tubuh, banyak lagi, beberapa membuatku meringis.
“Tidak semua melakukannya.”
“Kebanyakan melakukannya.”
“Kau tidak.”
Anwar melempar pandangan mencela.
“Aku tidak melakukannya.”
Ada nada bangga saat dia mengucapkannya. Beberapa obrolan kami saat petang kadang berulang layaknya pasangan yang mulai menua. Perdebatan yang terjadi juga tak pernah usai meski kami berjanji untuk tak melakukannya sesering sebelumnya.
Jemarinya jauh lebih kurus sekarang. Aku menepuk-nepuk punggung tangannya sebelum mengembalikannya. “Hanya selisih dua jam,” ujarku sekali lagi.
“Katakan itu pada orang sekarat, mereka akan sangat menghargai detik yang mereka punya.” Anwar mengedip, sekali lagi memeriksa jamnya, “Ini mengasyikkan. Kita harus sering berpindah untuk mengejar waktu yang lebih pagi.”
Aku urung tersenyum. Menahan cekat yang tersendat. Tak pernah nyaman jika Anwar kembali pada mode aku-akan-segera-mati-mari-kita-menyiapkan-kuburan-di-depan-halaman-oh-sebentar-sepertinya-aku-harus-mati-di-tempat-lain-mari-kita-jalan-jalan—yang biasanya akan berakhir pada aktivitas mengunci diri di kamar hingga keesokan hari.
Beruntung tak ada kamar yang bisa dikunci di dalam pesawat.
Mungkin ada, namun Anwar dan aku tak mampu membayar tiketnya.
“Kau belum menjawab pertanyaanku.”
Anwar berdeham, menghabiskan isi gelasnya. “Tentang jatuh dari pesawat?”
Aku mengangguk. Kumiringkan sedikit tubuhku.
Baru kusadari bahwa penumpang yang tadi ada di sisi Anwar telah pergi. Pesawat memang tak penuh jadi bisa saja dia merambah kursi kosong lainnya—untuk tidur, atau sekadar menghindari obrolan kami berdua: pasangan yang tak pernah berhenti bicara. Salah satu tipe teman perjalanan yang harus selalu dihindari.
“Kita akan terapung.”
Aku mengernyitkan kening.
“Kau tahu maksudku.”
Aku menggeleng. “Tentu tidak, kau harus menjelaskannya.”
Seorang pramugari dengan cekatan memungut mangkuk sup dari depan Anwar, tersenyum sopan namun seakan menanyakan apakah dia juga bisa sekalian mengangkut gelas—sekali mengayuh dua tiga pulau terlampaui. Anwar mengangguk paham meski terlihat sedikit enggan menyerahkan gelas kertasnya begitu cepat. Aku sendiri sudah sejak tadi mengembalikan sisa sup dan jusku—tentunya setelah mengisi komentar tentang keduanya pada lembar kuesioner penumpang yang terselip di dalam majalah; kuharap seseorang membacanya. Atau sebaliknya.
Pramugari itu berlalu dengan cepat, kepalanya cekatan berpaling ke dua sisi pada tiap langkah untuk memastikan tak ada gelas atau mangkuk yang terlewat. Senyumnya tetap melekat.
Luar biasa.
Mungkin Anwar perlu belajar tersenyum padanya. Aku tersenyum sendiri memikirkan ide itu.
“Katakanlah pesawat ini meledak,” Anwar membuka suara.
“Meledak?”
“Ya, meledak.”
“Seperti apa maksudmu? Meledak seperti kembang api? Di film selalu digambarkan bagian pesawat yang patah lalu sisanya berkeping-keping jatuh. Meledak tak cukup pas rasanya.”
“Tentunya bukan seperti kembang api.”
“Lalu seperti apa?”
“Apa skenario yang terbayang olehmu? Ini bukan bagian dari tulisan yang kau akan uji logikanya, kan?”
Aku tertawa mendengar nada kesal Anwar.
“Kupikir pesawat tak akan meledak di atas sini?”
“Oh, kau membicarakan tentang risiko yang lebih besar pada pendaratan dan lepas landas?”
Aku mengangguk. “Kupikir kita seharusnya aman di atas sini.”
“Menurutmu apa yang bisa menyebabkan pesawat ini jatuh—dan tidak meledak dalam proses itu?”
Aku terdiam. “Bisakah kita jatuh karena awan-awan?”
Anwar mengangguk. “Kurasa bisa. Kurasa aku pernah membacanya di suatu tempat.” Dia menggaruk lengannya perlahan. Aku bisa melihat warna kekuningan itu menyebar pelan terbagi oleh bekas jari-jari dan kemudian kembali menyatu. Anwar kembali berucap, “Lupakan pertanyaanku tadi. Menurutmu sendiri, apa yang terjadi saat kita jatuh?”
Sesaat yang terbayang olehku adalah tukikan tajam layang-layang yang dulu sekali sering aku mainkan saat kami masih duduk di bangku SD. Barisan awan-awan dengan mudah menampilkan sekelumit memori cengiran nakal Anwar setiap kali dia menarik benang kala angin menguat (di mana seharusnya dia mengulur benang) dan layang-layang akan secara otomatis tersentak mencari keseimbangan baru yang umumnya akan berupa gerakan menukik tajam. Atau putus sama sekali.
“Kita akan terapung,” tanpa sadar aku mengucapkannya. Lebih karena aku membayangkan layang-layang putus. Terayun tenang seakan melambaikan salam perpisahan pada seutas benang yang pernah begitu erat merangkulnya.
Apakah layang-layang bahagia?
Saat aku mengembalikan pandangan pada Anwar, dia sedang bertopang dagu mengamatiku. Tak ada senyum di sana.
“Apakah kau bahagia?” gumamku, setengah bertanya.
Anwar menarik tanganku, menggenggamnya di antara kedua tangannya sendiri. “Itu bukan pertanyaan untuk kita.”
Senyumnya terbit saat mengakhir kalimat itu.
Terdengar pengumuman tentang pesawat yang akan segera mendarat.
Anwar menyorongkan tubuhnya, mengintip. Ini pertama kalinya kami berkunjung di kota K. Raut wajahnya terlihat puas.
Aku turut memastikan. “Aku tak tahu kalau pohon kelapa yang berbaris bisa terlihat begitu menarik dari atas sini.”
Anwar tersenyum—kurasa kami memang harus sering bepergian.
“Kau yakin itu pohon kelapa?”
“Huh?”
Anwar menepuk punggung tanganku lembut. “Semuanya terasa menarik karena ada pembanding.”
Aku mengintip lagi. Tapi tetap tak mengerti.
Anwar menegakkan sandaran kursinya seraya berujar, “Tahu kenapa Tuhan membangun kerajaan-Nya tinggi di atas sana? Karena segalanya menarik dari kejauhan. Terlalu dekat—Dia pasti muak pada kita-manusia.”
Aku tak tersenyum. Guncangan pesawat semakin terasa.
“Sebenarnya sekarang saat yang tepat untuk membahas teori pesawat meledakmu,” balasku.
Anwar terkesima, aku tertawa sampai menutup mulut.
Saat itulah aku merasa terapung.
Kurasa Anwar juga.
—

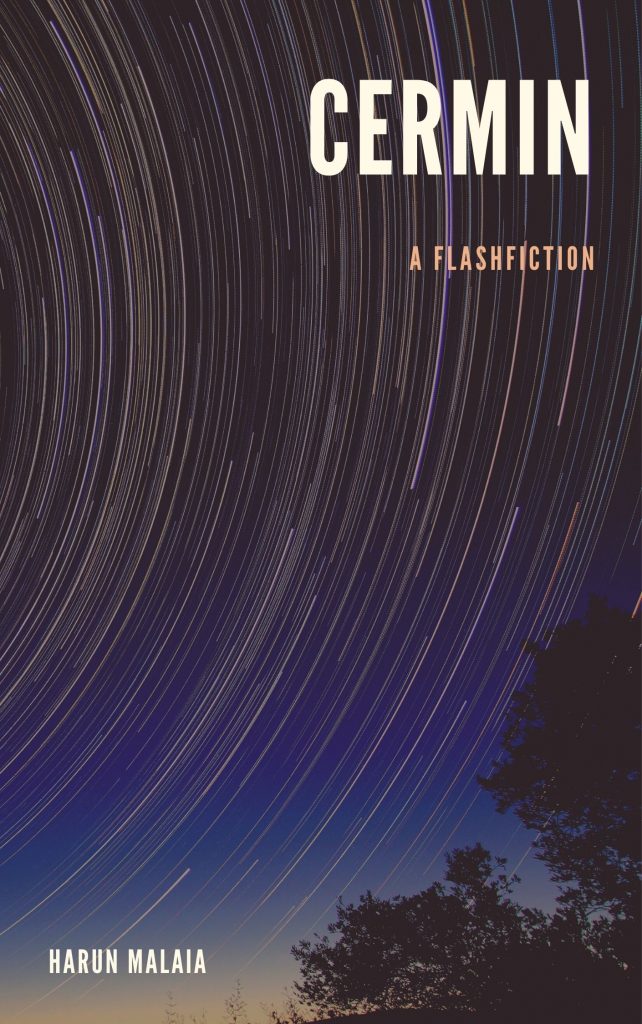

Tinggalkan Balasan