Kau terbangun dengan sentakan yang menyakitkan. Alih-alih beristirahat dengan tenang, belakangan ini tidur telah menjadi momok yang menakutkan.
Dua bulan terakhir, tepatnya.
Ya, kau yakin persis karena sejak mimpi itu berulang, kau telah menandai angka-angka di kalender dengan spidol merah. Silang berarti mimpi buruk; lingkaran berarti tidak adanya mimpi — atau tidak tidur sama sekali. Kau bahkan menandai berapa kali mimpi itu datang setiap malamnya, jika kau mampu untuk tidur lagi tentunya.
Semua berawal sejak kau mengambil keputusan yang salah sore itu. Seandainya bisa memutar waktu, kau pasti akan melakukannya. Kau pasti memilih untuk tetap tinggal di stasiun lalu menunggu kereta berikutnya, alih-alih memaksakan diri menyelinap di himpitan tubuh-tubuh berbau peluh berwajah lusuh.
Tapi bagaimana lagi, petang sudah menjelang dan tidak ada jaminan bahwa kereta berikutnya akan kosong melompong. Berbekal pemikiran itu kau akhirnya menggesekkan kartu perjalananmu.
Kau ingat persis bahwa saat itu hati kecilmu sempat melarangmu naik — jika memang hati kecil itu ada (kau termasuk orang yang tak mempercayai keberadaannya). Kau berpendapat perumpamaan ‘hati kecil’ itu hanya untuk orang-orang yang melankolis dan tidak mampu berpikir dengan otaknya. Hati kecil tahi kucing. Jika benar hati kecil itu penentu benar-salah tindakan seseorang, mengapa tidak jadi hati besar saja sekalian, ketimbang jadi setan penakut di sudut, mencebik tak karuan tapi sigap menyalahkan tiap ada tindak keliru yang kau lakukan.
Tapi sudahlah, kau tak ingin membicarakan tentang hati kecil. Tak ada gunanya. Kau sekadar ingin menegaskan bahwa di sore sialan itu, kau sebenarnya tidak sepenuhnya ingin memaksakan naik kereta yang penuh sesak itu — lagipula siapa orang waras yang mau? Kau sudah merasakan ada yang keliru. Tapi karena kau orang yang rasional seperti yang telah kau utarakan di atas dan kau tak percaya akan firasat ini-itu (apalagi hati kecil!), maka kau tetap melangkah naik.
Maka di sanalah kau, menyempil di antara badan-badan basah berkeringat. Setengah mati kau menahan diri untuk tidak memaki. Baunya saja sudah mencekik bahkan sejak pintu kereta belum tertutup rapat. Tentunya kau tetap senang hati memaki di dalam hati, pada babi-babi bau tak terperi yang mengepungmu, serta siapapun yang mengizinkan keadaan ini terjadi.
Kau ingat bahwa sore itu kereta berjalan sesuai jadwal, sudah hampir separuh rutenya, dan kau nyaris melupakan segala perasaan tak enak yang awalnya kau rasakan. Sebaliknya bahkan mulai merasa nyaman dan terbiasa dengan babi-babi di sekitarmu, kantuk mulai mendera dan kelopak matamu terasa berat. Kau ingat sempat merasa lucu betapa mudahnya kau beradaptasi dengan kehidupan babi-babi. Mungkin memang kau punya bakat untuk jadi salah satunya, atau memang kau punya ambang toleransi yang tinggi. Apapun itu, kau tak terlalu memikirkannya, karena pertimbangan tentang tidak naik kereta mulai kembali mengganggu ketika kau melihatnya.
Mimpi buruk itu.
Entah apa yang menarik matamu untuk melihatnya, kau sampai sekarang tak mengerti. Mungkin itu takdir. Entahlah (kau juga bukan seseorang yang percaya akan takdir). Kau percaya segala sesuatu yang terjadi bisa ditilik dari sudut pandang sebab-akibat.
Mungkin itu pula yang membuatmu terus-menerus bermimpi buruk. Kau masih mencari alasan menaiki kereta sore itu, lalu selanjutnya melihat mimpi buruk itu. Kau terus memutar pikiran, mencari tahu makna di balik kejadian memuakkan itu. Mungkinkah memang takdir? Takdir macam apa yang membiarkan seseorang bermimpi buruk setiap malam selama dua bulan? Bahkan bisa jadi akan lebih lama?
Takdir tahi kucing.
Apapun yang menyebabkannya, ketidaksengajaan atau takdir semata (ha-ha-ha) atau bahkan kombinasinya, intinya kau melihatnya.
Kau melihat: tangan kekar berambut kasar dalam balutan jaket jeans biru lusuh–jaket itu setengah tergulung di batas siku. Tangan itu bergerak perlahan, lepas dari pegangan kereta yang tergantung terayun-ayun pelan seirama laju kereta sore itu. Tangan itu kemudian berhenti di pundak seseorang yang ada di depannya. Halus sekali gerakannya. Semula kau mengira itu hanya gerakan tak sengaja yang tak memiliki arti saking tak kentaranya. Namun gerakan selanjutnyalah yang membuatmu terus memperhatikan. Tangan itu masih berada di pundak seseorang itu (kau tak bisa melihat wajah seseorang tersebut karena terhalang kerumunan, begitu juga wajah si pemilik tangan kekar berambut kasar dalam balutan jaket jeans biru lusuh setengah tergulung di batas siku). Tapi kau bisa melihatnya menggeser tubuh, jelas tak ingin ada tangan kekar berambut kasar tertahan di bahunya.
Tangan itu terjatuh dari pundak. Kau menahan napas. Entah mengapa, kau seperti tahu tangan itu tak berhenti sampai di situ saja.
Benar saja, kau lantas melihat tangan itu kembali bergerak naik, kali ini bergeser lebih maju. Menangkup dada dari belakang. Ketika itu bertepatan dengan kereta sedikit berguncang karena sambungan rel yang sedikit kasar. Kau tak melihat bagaimana kejadiannya, namun saat matamu kembali tertuju kesana, tangan itu sudah menangkup penuh dada itu.
Kau merasakan getaran aneh yang tak biasa. Napasmu tercekat.
Kau seperti merasakan seseorang itu juga sesak napas.
Tangan itu menggenggam lebih erat.
Meremas.
Kau menahan mual yang tiba-tiba menerjang. Hal terakhir yang ingin kau lakukan adalah muntah di badan babi-babi.
Kau ingat telah berusaha membuang pandang ke arah yang lain. Namun entah mengapa, pandanganmu kembali tertuju padanya. Seakan matamu dan tangannya adalah dua magnet dengan kutub berbeda.
Tangan itu mulai menelusup di sela-sela kemeja dan meraba apa yang ada di baliknya.
Punggungmu meremang.
Kau pikir itu terjadi karena melihat apa yang tangan itu lakukan. Sampai kemudian kau melihat ada mulut dengan bibir tebal-menghitam-kebanyakan-merokok yang mendekat. Berbisik di telinga seseorang itu.
Kau seakan merasakan seseorang itu mengejang. Terlihat dari gerak tubuhnya yang kaku dan janggal.
Kepalamu pusing dan kau mulai memikirkan untuk turun di pemberhentian selanjutnya. Namun sekali lagi magnet itu menarikmu.
Tangan kekar berambut kasar itu lalu bergerak ke bawah. Pelan–seumpama kegelapan turun di senja hari di luar kereta. Lambat–selayaknya kabut jatuh di perbukitan yang sepi. Tangan itu merayap turun, meraba, lalu menelusup. Sementara mulutnya di atas terus berbisik.
Tangan itu tak berhenti saat menemukan hambatan, ia terus menelusup turun ke bawah pinggang. Bibir di atas makin mendekat lekat.
Seseorang itu mengejang. Kau hampir kehabisan napas.
Lalu sontak magnet itu hilang. Kau seperti tersentak. Pandanganmu kosong. Bisa saja kau pingsan saat itu. Namun kau masih mampu menahannya. Pingsan di antara babi-babi jelas bukan pilihan. Menahan rasa mual dan sekeliling yang mulai berputar, kau menutup mata. Mencoba menghalangi gambaran mimpi yang masih terjadi. Meski entah kenapa kau seperti bisa merasakannya: tangan kekar berbulu, dan apa yang dilakukannya di bawah sana; mulut berbibir tebal itu, dan apa yang ia bisikkan di telinga.
Kau membuka mata.
Masih di arah yang sama, seseorang itu menatapmu iba.
Kau kembali menutup mata.
Namun terlanjur mimpi itu sempurna.
***

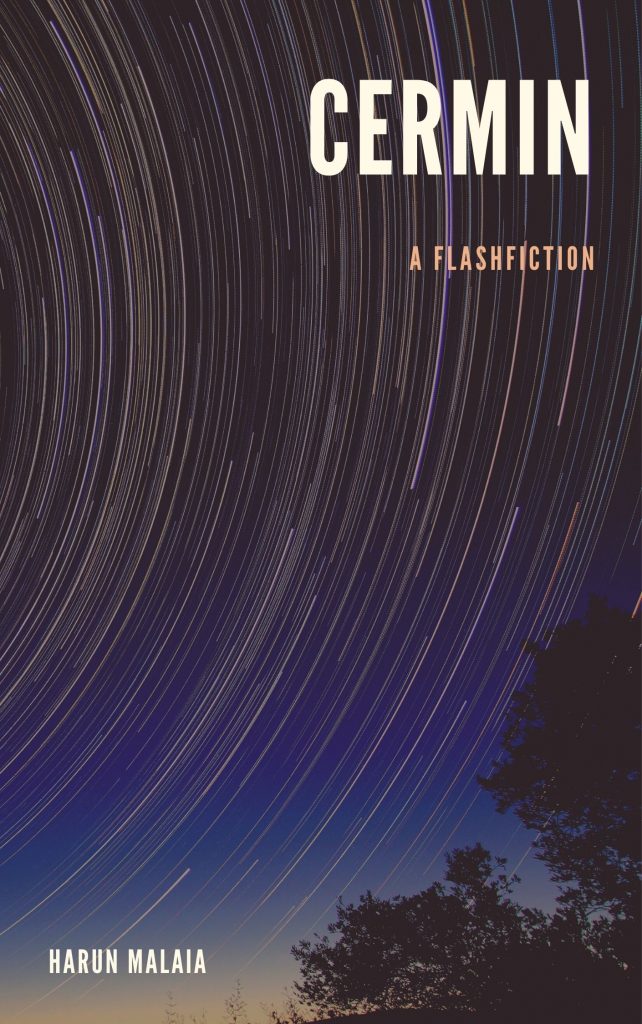

Tinggalkan Balasan