Tidak ada efek istimewa dari batu berwarna merah darah itu. Parijan yakin benar karena dia sendiri yang memungut ketiganya dari kolong jembatan tempatnya kencing berdiri tempo hari. Belakangan memang dia sering kebelet kencing — dokter di Puskesmas pernah bilang mungkin gejala kencing manis, tetapi setelah diperiksa kencingnya baik-baik saja, dokter tersebut bilang mungkin infeksi saluran kemih. Parijan belum periksa lagi setelah obatnya habis. Apalagi kini kencingnya sudah jauh lebih teratur, jadi mungkin obat itu benar berefek. Sedangkan batu tersebut? Mungkin saja warnanya menarik karena kini sering dibersihkan berkala, namun pertama kali mendapatinya, Parijan bahkan berpikir batu itu mirip sekali batu bata yang kebanyakan dikencingi.
Atau karena mengandung air kemih sehingga punya efek menyembuhkan?
Entahlah. Parijan pun tak mengerti. Yang jelas, semenjak seorang kakek tua dengan keluhan lemah syahwat berkoar-koar bahwa tiga batu mirah delima tersebut yang telah menyembuhkannya, Parijan mendapati barisan orang telah antre di halaman rumahnya bahkan sejak pagi buta.
“Sholat subuh dulu, Pak, Bu.” Demikian biasanya dia menyapa.
Sepulang dari masjid barisan tersebut bahkan telah mengular keluar pagar. Istrinya sampai kebingungan.
“Gula pasir sudah habis, Pak,” adunya.
Istrinya memang biasa menghidangkan teh dan kopi untuk mereka yang menunggu. Parijan garuk kepala dan memberi beberapa lembar sepuluh ribu.
“Mungkin kita harus batasi pasien setiap hari, Bu.”
Menyebut pasien juga bukanlah idenya. Adalah Pak Karto, tetangga dari kampung sebelah yang mengaku-aku sebagai pasiennya. Meski testimoninya tidak sedahsyat kakek lemah syahwat, Pak Karto yang paling sering bercerita dan menyebarkan info khasiat batu mirah delima.
“Saya sudah lama jadi pasien Parijan. Sudah jauh lebih enakan.”
Keluhannya adalah encok menahun. Yang Parijan sendiri yakin akan jauh lebih berkurang sekiranya Pak Karto mau menurunkan berat badannya sedikit.
Membatasi pasien juga bukan ide cemerlang rupanya. Begitu tahu pasien dibatasi dua puluh orang saja setiap harinya, mereka antre jauh lebih awal dari biasanya. Malam itu, saat Parijan sedang memeluk istrinya selesai malam Jumat, mereka mendengar pintu pagar digeser. Bersungut-sungut mengencangkan sarungnya, Parijan turun dari tempat tidur dan membuka pintu depan.
“Pagi, Pak Parijan.” Sudah tiga orang duduk tenang di teras rumahnya. Salah satunya tampak asyik mengoles losion antinyamuk di lengannya.
Di luar semua rutinitas baru yang kadang mengagetkannya itu, Parijan sebenarnya bersyukur. Dia memang tidak pernah meminta dibayar banyak untuk tiap pasien yang ditolongnya. Saat dia masih jadi tukang pijat, dia menaruh tarif lima puluh ribu. Dengan terapi batu mirah delima, dia hanya menambahkan biaya dua puluh ribu. Itu pun sudah diberi bonus teh atau kopi dan kudapan ringan.
Istrinya yang sedikit kerepotan. Wanita itu sampai harus mencari rekan tambahan yang bisa membuat beragam camilan. Ibu-ibu tetangganya dengan senang hati membantu, apalagi saat tahu setiap kue dihargai dua ribu perak.
Mungkin saja karena tergolong murah, pasien terus berdatangan. Padahal kalau mau saling jujur, terapi batu mirah delima Parijan sebenarnya tidaklah luar biasa. Awal ceritanya, Parijan baru jatuh dari motor, pergelangan kirinya terasa sakit jika dipaksa memijat kencang; sudah beberapa pelanggan mengeluhkan kalau pijatannya kurang maksimal. Jadi selama beberapa hari Parijan memutar otak agar tetap bisa bekerja, apalagi saat obat penghilang nyeri dari Puskesmas tak begitu manjur dirasakannya. Hingga pagi itu, istrinya tak sengaja menambahkan air panas terlalu banyak untuk mandi. Parijan merasa nyerinya berkurang saat merendam tangannya di air suam-suam kuku.
Dicobanya melumuri balsam pijat, tapi tak sama rasanya.
Pun saat menempel beberapa lembar koyo cabe, yang ada lengannya melepuh.
Tak mungkin merendam tangannya terus-terusan saat memijat.
Lalu istrinya iseng membuat kompres air hangat dengan plastik bening bekas pembungkus gula pasir, memang enakan, tapi tetap sulit dipakai bekerja.
Sore sudah menjelang saat akhirnya Parijan berhasil menemukan pengganti kompres air hangat yaitu koin logam yang dibakar.
Hanya saja istrinya tak suka dia membuang uang — maka dicarikannya semacam pengganti logam atau arang. Parijan sampai tertawa saat istrinya mengusulkan menggunakan kayu bakar.
“Ibu pikir saya Nabi Ibrahim?”
Coba dan gagal terus terjadi selama beberapa hari. Selama itu pula pasien pijat Parijan terus berkurang. Parijan telah mencoba mengganti semua bahan untuk ditempel di pergelangannya. Daun gatal ditumbuk. Kunyit. Bawang. Jahe. Cabe rawit.
Batu.
Sebelumnya sudah beberapa batu dia pakai, namun tak banyak dari batu itu yang tahan dibakar. Beda dengan batu mirah delima ini. Hanya dipanggang sebentar, panasnya merata dan tahan lama. Ukurannya yang agak gepeng seukuran biji salak juga sangat pas. Benar-benar mujur. Parijan minta istrinya menempel tiga batu tersebut di pergelangannya, membalutnya dengan secarik kain. Nyeri di lengannya berkurang dan dia kembali dapat memijat dengan kekuatan yang memuaskan.
Lalu seorang pelanggan yang sedang dipijat, iseng menanyakan kenapa pergelangan tangannya dibalut. Pelanggan itu sendiri kemudian yang ingin mencoba terapi tersebut.
“Yah, siapa tahu nyeri pinggang saya juga berkurang, kan, Pak?” kekehnya saat itu.
Parijan ingat sampai harus meminjam selendang istrinya saat itu, supaya bisa membalut pinggang si pelanggan, saking besarnya.
Ya, itu pinggang Pak Karto.
Beberapa mantri dan suster dari Puskesmas jadi lebih sering berkunjung. Mereka banyak bertanya. Parijan menjawab seadanya.
“Efeknya apa saja ya, Pak?”
Parijan mengangkat bahu. “Yah, jujur, saya kurang tahu, Pak Mantri. Selama ini cuma untuk mijet.”
“Tapi katanya bisa merontokkan batu ginjal, lho,” timpal ibu suster satunya. Dia hanya datang menemani sebab Parijan tak menerima pasien perempuan.
“Wah, saya nggak pernah bilang begitu, Bu.”
Tidak menerima pasien perempuan sempat jadi sedikit masalah. Parijan sempat diprotes sok alim, padahal pasien-pasien itu sudah lama antre.
“Kan tetap ditemani pas mijetnya, Pak. Jadi nggak berdua-duaan saja.”
“Saya nggak bisa mijat perempuan, maaf…” Parijan sampai harus berulang-ulang menjelaskan.
Singkat cerita, meski tak pernah ada penjelasan yang pasti tentang efek batu mirah delima milik Parijan, kabar tentang khasiatnya sudah menyebar ke mana-mana. Warga kampung sebelah, kanan dan kiri semakin ramai berkunjung. Buntutnya, Parijan terpaksa membeli beberapa pasang kursi plastik untuk ditaruh di depan teras. Sekali waktu, dia juga dibantu beberapa orang tetangga menebang rumpun-rumpun bambu yang menyemak di sudut halaman. Sisa potongannya yang besar dia pakai untuk membuat balai-balai kecil sebagai tambahan tempat duduk.
Karena keramaian yang terus bertambah di sekitar rumah Parijan, warga kampung juga ingin kecipratan. “Saya boleh dong numpang jualan cendol, Pak.” Meski diucapkan dengan nada bergurau, sebenarnya Mbok Minah serius.
Jualan cendol Mbok Minah segera disusul camilan-camilan lain yang dijajakan warga. Sekitar jam tujuh pagi mereka mulai datang bergantian. Menjelang siang biasanya ada yang berjualan nasi bungkus. Meski demikian, Parijan tetap menyediakan teh kopi gratis. Sungguh layanan yang bikin betah.
Jika pun ada yang masih dikeluhkan pasien, tentu sinyal internet yang tidak bagus di pelataran rumah Parijan. Malah bisa dibilang tidak ada. Akibatnya mereka terpaksa saling mengobrol sesama pasien.
“Saya sudah coba bekam tujuh kali. Iya, sampai saya kurang darah katanya. Tapi belum ada perbaikan.”
“Coba ke sinse yang sana sudah, belum?”
“Toko buku yang di seberang Pasar Suka Untung sudah lama tutup?”
“Ya ampun, ternyata sampeyan cucunya Pak Broto? Yang pernah tinggal di Jalan Kawi? Yang suka diajak ngangon kambing?”
“Kalau memang cocok, mulai minggu depan sudah boleh kerja di tempat saya dulu anaknya. Daripada nganggur nunggu pengumuman pegawai negeri.”
Parijan tidak punya anak. Jadi riuh rendah pasien dari subuh hingga petang menjelang tidak terlalu diributkannya. Yang jadi persoalan justru ketika suatu hari, seseorang dari surat kabar dan televisi datang berkunjung.
“Kita ingin meliput metode pengobatan Bapak. Nanti Bapak masuk televisi.”
Parijan menjelaskan sebisanya. Dia menolak liputan televisi karena membuatnya gugup dan beberapa kali harus permisi kencing. Namun surat kabar tetap meliputnya, beberapa orang yang jadi pasien juga dengan senang hati berkomentar sebagai tambahan bahan tulisan.
Tak pelak beberapa waktu setelahnya, semakin ramai warga berkunjung, memang tidak semuanya sedang sakit, kebanyakan hanya penasaran. Di antara mereka terdapat beberapa orang dari bagian perizinan usaha dan yang mengaku peneliti obat-obatan. Mereka turut bertandang. Mereka sedikit mempermasalahkan ketiadaan izin usaha Parijan.
“Bapak sudah melayani berapa banyak pasien? Tapi tidak sedikit pun usaha untuk mengurus perizinan?”
Parijan manggut-manggut, dia membisiki istrinya untuk mengingatkannya mendaftar usaha pijat.
“Bukan usaha pijatnya, Pak. Bapak kan sudah melayani dengan batu mirah delima. Harus dicantumkan dong keterangannya. Mengobati penyakit apa. Efeknya seperti apa. Berapa lama jangka waktunya. Biar jelas! Biar tidak ada yang merasa tertipu setelah datang kemari! Puskesmas saja sampai sepi gara-gara usaha Pak Parijan.”
Beberapa pasien yang sudah menunggu lama protes. Pasalnya orang-orang tersebut tidak antre dari subuh. Tidak mau kalah, orang dari peneliti balas mengancam. “Bapak-Ibu yang tidak tahu urusan diam dulu, ya? Bisa saja batu ini beracun. Punya efek samping jelek untuk tubuh Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Siapa yang mau tanggung jawab?!”
Pasien rata-rata diam. Lirih dalam gumam.
“Begini saja Pak Parijan. Batunya kami pinjam dulu. Akan kami teliti. Nanti kalau sudah jelas kandungan dan efeknya, kami kembalikan kepada Bapak.”
“Pak Parijan juga sebaiknya hentikan dulu usahanya sampai surat izinnya keluar. Harus jadi warga negara yang baik, dong, Pak. Malu sama warga yang berkunjung.”
Bapak dari perizinan memberikan selembar kertas. Parijan menghitung sekitar sepuluh atau sebelas poin syarat yang harus dia ajukan. Diangsurkannya surat tersebut kepada istrinya.
“Jadi batunya dibawa sekarang, Pak?” Parijan bertanya memastikan.
“Iya dong, Pak. Kita nggak punya waktu untuk bolak-balik sejauh ini. Nanti kalau sudah ada hasilnya, kita kabari.” Bapak peneliti menyodorkan formulir. “Bapak isi dulu surat keterangan pengambilan sampel ini. Pokoknya ya berdoa saja hasilnya bagus. Jadi Bapak bisa lanjut usahanya lagi.”
Sudah sekitar empat bulan berselang sejak mereka datang. Parijan belum mendengar kabar tentang batu mirah delimanya. Satu demi satu pasien yang dulu ramai mulai hilang, terlebih karena mereka rata-rata hanya penasaran dengan batu yang katanya mujarab itu. Beberapa menyayangkan kenapa Parijan dengan mudahnya menyerahkan batu tersebut. Beberapa yang lain juga sedikit kecewa karena kini lapaknya jadi sepi.
Yang bertahan hanyalah pasien pijat yang memang biasa dilayani Parijan. Apalagi kini setelah pergelangan tangannya benar-benar pulih, pijatannya kembali enak. Hasil melayani pasien batu mirah delima selama kurang lebih lima bulan juga lumayan banyak berhasil dikumpulkan oleh istrinya yang memang terkenal hemat. Dibelikannya alat-alat pemanggang kue dan mulai berjualan keliling kampung, mendatangi pelanggan yang dulu kerap memenuhi halaman rumahnya. Karena memang penganan bikinan istri Parijan enak, pembelinya tetap ramai.
Sore itu, saat Parijan sedang tidak ada pasien pijat, dia menemani istrinya berkeliling mengantar kue. Disapanya wajah-wajah yang tak asing. Sesekali beberapa dari mereka masih bertanya, “Apakah sudah ada kabar batu mirah delima?”
Parijan maupun istrinya hanya menggeleng. Meski kemudian dalam perjalanan pulang, Parijan kembali kebelet kencing di tepi jembatan, dia melihat sesuatu berwarna mencolok di bawah sana. Persis saat pertama kali dia melihatnya. Tiga batu berwarna merah menyala. Mirah delima.

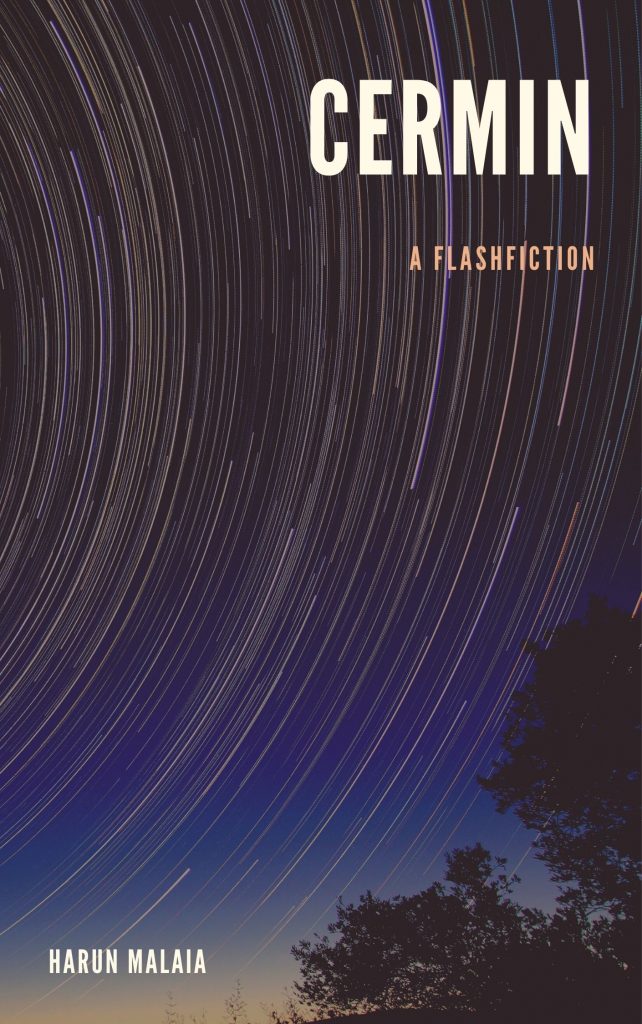

Tinggalkan Balasan