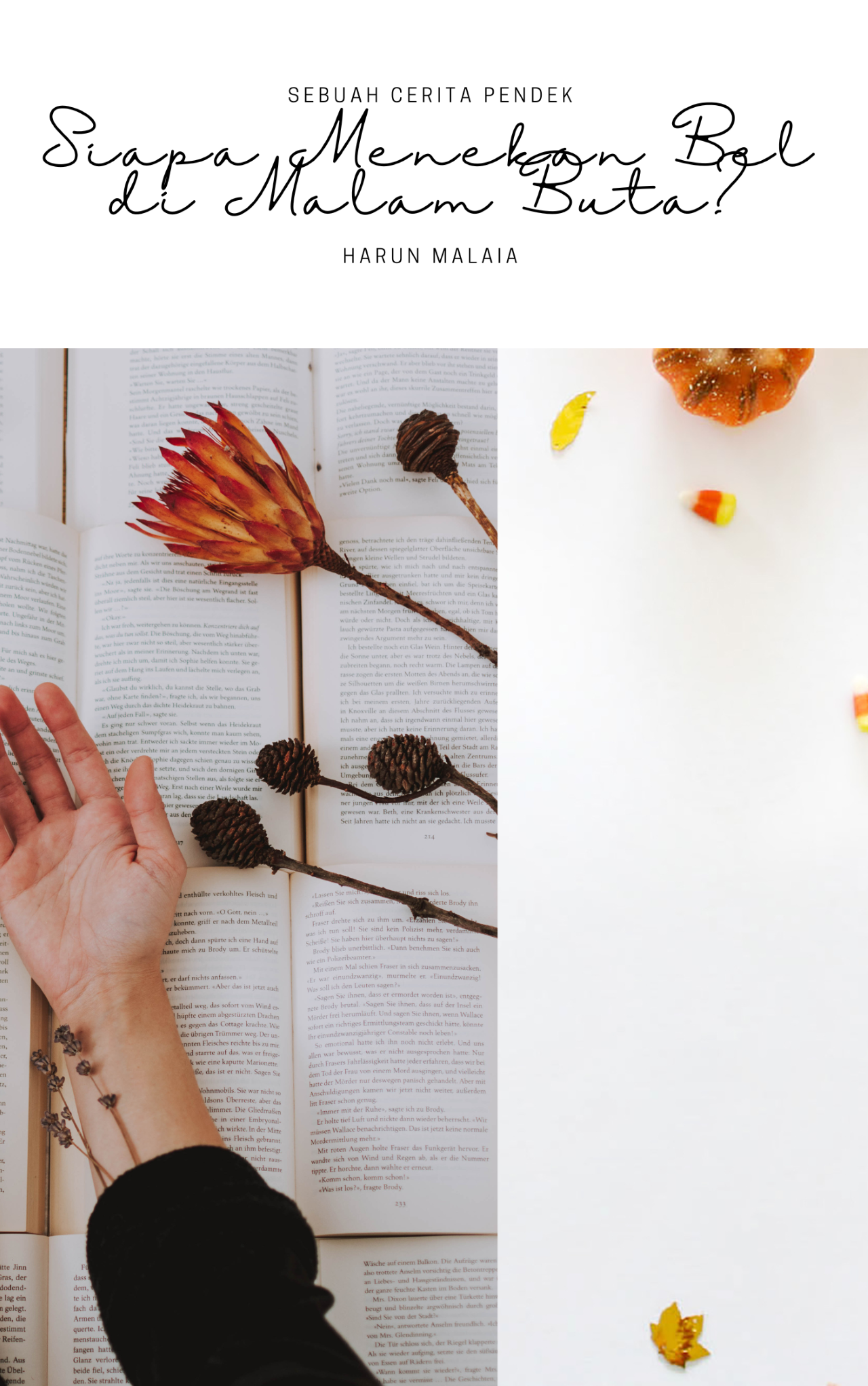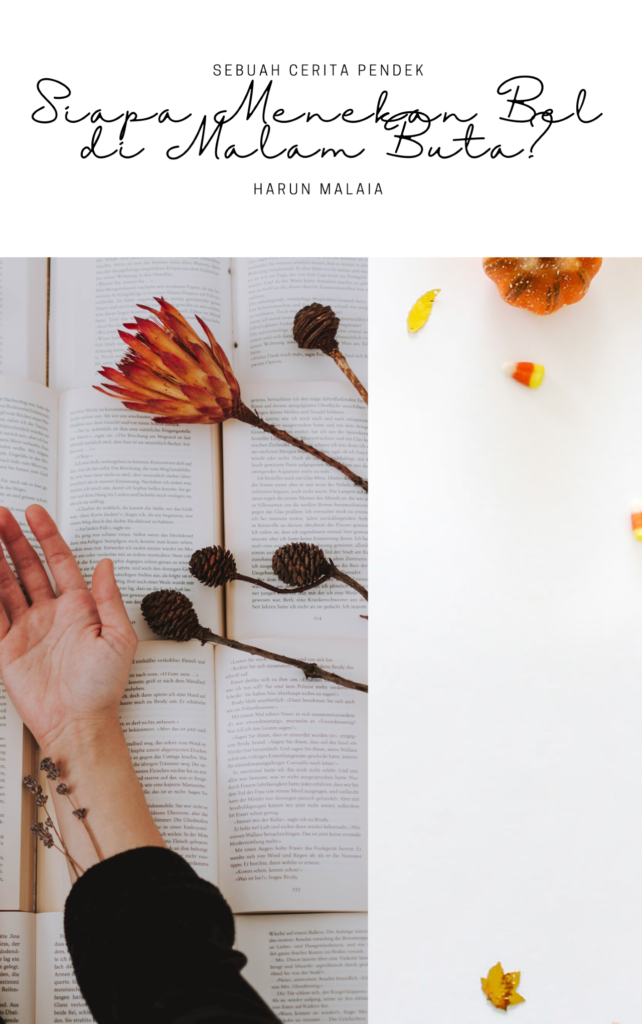
Mama histeris lagi. Saat aku bangun kudapati tiga puluh sembilan missed calls darinya. Semua dilakukan sebelum jam lima pagi. Malam buta! Ada juga beberapa pesan yang tak ingin kubuka. Lebih baik segera kutelepon.
Mama mengangkat pada dering pertama dan suaranya melengking, “Seseorang menyentuh jendela kamarku!” Dia memberi penekanan pada tiap suku katanya.
Kamar Mama di lantai dasar, terdapat dua pasang jendela di sisi timur dan selatan yang memang memiliki tambahan teras. Pagar setinggi pinggang dengan kawat berduri memisahkannya dengan halaman di sekitarnya. Belum lagi beberapa petak rumpun mawar yang sengaja ditanam dan terawat baik sebagai pagar pelindung alami. Jadi rasanya mustahil jika seseorang bersusah payah hanya untuk menyentuh jendela kamar Mama, tapi kubiarkan saja Mama terus bercerita.
“Ada tiga belas telapak tangan, bernoda lumpur! Tiga belas! Aku menghitungnya sendiri. Kurasa ada yang bernoda darah! Di jendela kamarku!”
Aku terus mendengarkan keluhan Mama sampai sekitar sepuluh menit berikutnya. Ketika dia sudah mulai tenang, kukatakan kalau akan kuperiksa jendelanya selepas makan siang. Sif malamku berakhir nanti jam delapan.
Mama terdengar senang. “Saat kau pulang, bawakan aku dua potong brownies dari kedai Nyonya Meulia. Dan permen.”
Aku mencatat pesanannya, meski aku tak akan membelikannya permen. Sejenak aku berpikir tentang makanan pengganti yang mungkin kubelikan. Kuputuskan akan singgah di toko buah yang jaraknya tak jauh dari kedai Nyonya Meulia.
“Ada lagi yang Mama mau?”
Mama tak langsung menjawab, tapi aku tahu dia sedang berpikir karena telepon gemerisik selama beberapa waktu. Napasnya terdengar satu-satu.
“Mama?”
Dia berdeham sesekali. Terdengar ketukan-ketukan kecil, mungkin Mama sedang memainkan gagang telepon. Aku baru akan bertanya lagi saat jawabannya tiba.
“Itu saja.”
Lalu dia menutup sambungan.
***
Sudah hampir dua tahun Mama tak berani keluar rumah. Dia selalu ingin keluar, tapi paling jauh lima langkah melewati pintu depan, lututnya mendadak goyah dan dia—dengan sejuta alasan untuk memutar badan, kembali ke dalam rumah.
“Napasku sesak, mungkin aku perlu duduk-duduk sebentar.”
“Kurasa aku lupa mematikan keran air kamar mandi.”
“Aku lupa ada rekaman telenovela yang belum aku tonton.”
“Kurasa akan segera hujan, lebih baik kita ngobrol di kamarku.”
Meski kami sama-sama tahu bahwa itu semua hanya alasan palsu dan alasan sebenarnya Mama tak ingin keluar adalah dia semakin tak percaya orang-orang di sekitarnya, kami berdua tak membicarakannya lebih lanjut. Mama tak ingin aku mencampuri kecemasannya. Sedangkan aku, meski sedikit merasa berdosa karena mendiamkan hal itu, harus mengakui bahwa aku tak selalu cukup sabar untuk mendampingi kecemasannya.
Jadi, kami sama-sama diuntungkan kalau mau jujur.
Ada saja pikiran buruk yang segera menghinggapi Mama jika dia keluar rumah. Hal yang lucu tentunya, mengingat dia sama sekali tak punya pikiran seperti itu jika sudah di dalam rumah. Seakan-akan ada tabir pelindung kasat mata yang membentenginya dari dunia luar. Persis di depan pintu.
Ya, kurasa Mama mungkin benar-benar merasa seperti itu. Rumah ini gelembung dan Mama senang di dalamnya. Kukatakan gelembung karena tentu saja cepat atau lambat dindingnya akan pecah dan suatu saat Mama harus menghadapi dunia luar sana.
Hanya saja, selama Mama merasa aman dalam gelembungnya, aku tak terlalu banyak pikiran. Dan itu sudah lebih dari cukup.
***
Segalanya memburuk dua bulan terakhir. Ketika Mama mulai tak ingin keluar kamar. Bukan lagi rumah.
Ya, aku ingat karena membuat silang merah di kalender gantung. Pertama kali dia menelepon di malam hari dan mengatakan ada seseorang membunyikan bel pintu depan.
“Tapi ini jam satu malam, Mama.” Dan aku tak mendengar apapun di luar sana. Namun ucapan itu aku telan saja.
“Justru itu. Apa kau pikir hantu sudah bisa membunyikan bel?”
Kami tinggal serumah, kamarku di lantai atas. Aku baru pulang sif sore saat itu dan sejujurnya kepalaku pening dan tak ingin ribut dengannya, tapi karena tak tahan, kukatakan padanya itu semua khayalan dan Mama mendengar sesuatu yang lain. Perempuan itu mendiamkanku selama seminggu, dan baru mau bicara saat aku membawakan sekantung permen kesukaannya.
Mama juga sudah tak mau lagi pergi beribadah. Dia bilang terlalu banyak cahaya di tempat-tempat itu dan semua mengingatkannya pada kematian.
“Jika mati aku yakin mereka tak datang di kuburanku.”
Aku menahan diri untuk tidak memutar bola mata di depannya.
Satu dua kali teman-teman lama Mama menanyakan keberadaannya padaku, karena aku anak satu-satunya. Kucoba menjelaskan dan aku bersyukur setengah mati karena kebanyakan dari mereka memahami keadaan Mama. Pernah beberapa orang datang ke rumah, sekadar duduk-duduk dan bercerita. Pulangnya, Mama meninggalkan pesan singkat di handphone.
‘kurasa Nyonya Tulita hanya ingin mencuri bunga anggrekku. dia tak henti-henti meliriknya (oh, aku benar-benar melihatnya—tentunya dia tak menyadari itu). dan saat kami berbincang, dia terus menyinggung betapa indahnya bunga itu. oh, kuharap dia berhenti mengunjungiku.’
***
Salah seorang teman lama Mama, tinggal tak jauh dari kami, adalah dokter spesialis jiwa. Kucoba mendekatinya, dan menceritakan sedikit banyak tentang Mama.
“Apakah pernah terjadi sesuatu yang membuat ibumu khawatir?”
Aku mencoba mengingat-ingat. Mama memang selalu khawatir. Bahkan sejak ingatan kanak-kanak pun, aku tak bisa mengingat kapan Mama tak khawatir.
“Jangan panjat pohon itu, kau bisa terluka.”
“Jangan berteman dengan Teddy dan Lily, mereka sering mengumpat dan sekali lagi kudengar kau menirukannya, aku akan menaruh cabe besar-besar di dalam roti isimu.”
Atau saat berbincang dengan mendiang Papa.
“Kurasa anak kita itu memang tak cerdas. Setengah mati aku mengajarinya, tapi mungkin kepalanya benar-benar kosong—yang mana seharusnya bisa diisi, tapi ini kosong yang membuatmu muak. Oh, aku tak tahu harus lakukan apa dengannya.”
“Bisakah kau meminta kenaikan gaji? Kau sudah bekerja di sana berapa lama—dua puluh tahun? Tapi hanya ini saja yang kau bawa pulang.”
Pelan-pelan aku mencoba menceritakan tentang Mama kepada dokter itu, beberapa hal yang terlalu memalukan tentu tak kusampaikan. Perempuan ringkih dengan rambut memutih, tapi matanya bijak seperti telaga tak berpenghuni itu mengangguk-angguk dan sesekali membetulkan kacamatanya yang bertengger di ujung hidung.
“Apakah memungkinkan jika aku mengunjungi ibumu sesekali?”
Aku ragu-ragu menjawabnya. Pertama, jelas Mama tak akan suka. Kedua, aku tak punya cukup uang untuk membayar dokter ahli jika konsultasi ini dilakukan secara normal. Untuk alasan pertama aku coba utarakan secara perlahan. Beruntung, dokter itu memahami situasiku—dan alasan kedua.
“Tidak usah bayar. Aku sebenarnya sudah lama pensiun. Dan mungkin ini jalan untukku terus melayani. Aku juga memang sudah lama tak bertemu ibumu.”
Oh, besar hatiku mendengarnya. Jika tak ingat bahwa saat itu kami masih berada di persimpangan jalan, sudah kupeluk erat-erat dokter itu. Alih-alih, aku menggenggam tangannya dan mengucap terima kasih banyak-banyak.
Karena dokter itu tak bisa serta merta mengunjungi Mama, aku memberikan laporan secara berkala: apa saja keluhan Mama, begitu juga dengan hal-hal baru yang Mama takuti. Termasuk coretan di kalendar yang sekarang sedang kupandangi.
Mama mulai menelepon di tengah malam. Dua bulan lalu.
Mama melaporkan bel ditekan orang di tengah malam. Dua bulan lalu.
Mama memberhentikan Pascal tukang kebun. Satu bulan lalu.
***
Pascal patah hati saat Mama memberhentikannya. Meski dia tahu kondisi Mama sejak lama, kurasa dia tak menduga kalau dia akan termasuk orang yang pada akhirnya ditakuti oleh Mama. Pascal sebaya denganku, ayahnya yang pemabuk sering menempeleng kepalanya. Kurasa itu mengakibatkan otaknya tak begitu pintar. Untuk urusan itu, kami berdua senasib jadi secara otomatis berteman sejak kecil. Jika ayahnya mabuk dan kembali menempelengnya, Pascal kabur dan bersembunyi di rumahku dan kami berdua akan makan jagung bakar yang dibuatkan mendiang Papa.
Mama akan mengomel dan bilang bisa jadi suatu saat keluarga kami dibunuh oleh ayah Pascal karena sering turut campur.
Mungkin malaikat lewat saat itu sehingga ketakutan Mama benar-benar terjadi, tidak semua tapi tetap terbukti.
Suatu sore, ayah Pascal mabuk berat, berkali-kali lipat dari biasanya, datang menggedor pintu dan mencari Pascal. Papa mencoba menenangkannya namun pria itu tak mau tahu dan ketika tak menemukan Pascal di rumah kami—memang saat itu Pascal sedang bersembunyi di tempat lain. Pria itu mulai menarik-narik rumpun mawar Mama dan saat itu Mama meneriakinya ‘orang gila’. Entah bagaimana ayah Pascal bisa tersinggung, mengingat dia mabuk seperti pelaut, dia lantas mengayunkan sekop kebun menghancurkan jendela Mama. Papa yang berusaha menghentikannya tak begitu beruntung karena ayah Pascal terpeleset tanah kebun yang licin dan tak sengaja sekop kebun itu menghujam leher Papa dengan begitu keras. Papa tak tertolong, dia meninggal tersedak gumpalan darahnya sendiri.
Ayah Pascal mendekam di penjara dan tak pernah kembali. Pascal kemudian diasuh bibinya yang tinggal di seberang sungai, tapi karena bibinya senang mengomel, anak itu tak pernah betah. Ketika dia sudah bisa memasak sendiri, anak laki-laki itu pulang kembali ke rumahnya, hidup sebatang kara.
Lalu muncul suatu sore di pintu depan rumah kami, “Bisakah aku bekerja membersihkan halaman?”
Pascal menanyakan setiap rumah pertanyaan yang sama. Jadi, meski tak besar upah yang didapatkannya dari Mama, total lembar-lembar yang ia terima sehabis memotong rumput atau memindah-mindahkan posisi pot bunga dari rumah-rumah yang lain memungkinkannya untuknya hidup. Bahkan sampai sekarang. Saat kami bukan lagi anak kecil yang tertawa-tawa memungut dan menyuap butiran jagung bakar yang terlepas dari tongkolnya.
Jadi saat ia menangis karena diberhentikan Mama, kupikir pasti karena sebab yang lain, bukan karena kehilangan upah.
“Aku suka padamu. Sekarang apa alasanku datang menemuimu?”
Wajahku panas mengingat momen itu. Aku tak ingat bagaimana Pascal berani mendekatkan wajahnya ke wajahku dan kami duduk lama di samping mesin cuci tempatku bekerja sebagai pegawai laundry.
***
Dokter ahli jiwa itu mengatakan bisa jadi Mama mengidap paranoid. Sedikit yang mengganggu pikiranku adalah karena dia menyebutkan bahwa kondisi ini bisa terus memburuk.
“Dia akan curiga setiap saat. Pada setiap hal. Pada setiap orang.”
“Tapi Mama tak mungkin curiga padaku, kan?”
Aku ingat wajah kasihan yang seketika muncul di wajah dokter tua itu. Kurasa dia tahu yang sebenarnya, meski aku belum cerita. Empat hari yang lalu, Mama menolak makanan yang kusiapkan.
“Aku melihatmu menambahkan sesuatu yang tak biasa ke dalamnya. Apa kau sedang ingin membunuhku?”
Aku memang menambahkan bumbu baru ke dalam supnya. Tapi itu kulakukan karena bumbu yang biasa digunakan sudah tak lagi diproduksi dan tak bisa kudapatkan lagi di mana-mana meski aku berkeliling dan rasanya betisku mau patah. Pascal yang menyarankan untuk menggantikan bumbu itu dengan bumbu lain.
“Ini rasanya hampir sama. Aku sering pakai ini saat memasak. Harganya juga sedikit lebih murah.”
Aku ingat menangis di sudut dapur sambil memungut pecahan mangkuk yang Mama lemparkan di wajahku saat aku memaksanya makan. Aku tak cerita pada dokter tentang hal itu karena kupikir itu hanya kesilapan Mama. Dan memang kurasa dia tak sepenuhnya curiga padaku.
Karena selama tiga hari ini dia bersikap manis padaku. Meski tak meminta maaf, tapi dia mengingatkanku untuk mengganti perban di dahiku jika aku habis mandi—tentu saja semua ini dilakukannya lewat telepon. Sempat terpikir olehku apa Mama lupa kalau dia yang menyebabkan kepalaku luka?
Aku juga tak cerita pada dokter kalau Mama sempat menyinggung agar aku berpacaran dengan pria baik-baik, dan dia secara tegas menyebutkan Pascal bukan pria baik-baik.
“Dia terlihat baik tapi punya darah buruk. Dan darah itu akan mengalir selama dia hidup.”
Aku mengerti mungkin Mama masih dendam perihal kematian Papa. Sehingga aku mendiamkannya.
Dokter tua itu sempat berpesan sebelum meninggalkan bangkunya–kami sedang duduk-duduk di bangku taman. Dia terlihat menimbang-nimbang sambil melihat-lihat catatan kalendar yang kuberikan padanya. Memang memburuk, demikian ujarnya.
“Pastikan saja ibumu tidak menggunakan benda-benda tajam di dapur dan semacamnya. Kita tidak tahu apa yang besok-besok ada di pikirannya.” Dokter itu sempat menepuk bahuku pelan. “Jaga dirimu baik-baik, gadis muda.”
Aku tersentuh oleh perlakuannya, dadaku waktu itu menghangat. Diam-diam kucatat ucapannya.
Benda tajam.
Ya, akan kupastikan benda itu ada di dekat Mama malam ini.
Jika tiga belas telapak tangan bikinan Pascal itu tak cukup, mungkin aku perlu mendorongnya lebih jauh…
***selesai***