Jam berapa?
Sekilas tak ada yang janggal dari jawabannya atas pertanyaanku barusan. Ia menjawab ringkas, lalu tersenyum, sebelum sekali lagi menatap jam tangannya. Yang lain mungkin mengira ia sedang memastikan jawabannya tak keliru.
Tapi aku tidak.
Aku tahu pasti alasannya. Ia sedang mengenangnya. Wanita yang pernah mengisi hatinya, dan waktunya. Aku menyadarinya saat ulang tahun hari pernikahan kami, ia menyimpan hadiah jam tangan yang kuberikan dan kembali mengenakan jam tangan lamanya.
Aku terlanjur terbiasa, ujarnya.
Ia tidak berbohong. Aku tahu ia terbiasa melakukannya. Membaca perbedaan waktu lebih dari setengah hari.
Ya, jam tangannya menunjukkan waktu wilayah wanita itu berada. Pernah berada. Kadang, jika suasana hatiku sedang tidak baik, menyadari ia masih memikirkannya akan membuatku sedih dan sakit kepala. Beribu pertanyaan laju meragu dan berakhir pada satu retoris.
Kurangku apa?
Aku tak pernah berani langsung bertanya, tentu saja. Terlalu mudah untuk dijawab.
Tapi jika aku sedang tak cemburu, tak jarang kubayangkan betapa bahagianya andaikan aku yang ada dalam benaknya setiap kali ia mengusap dan mengamati jam tangannya. Ah, membayangkannya saja sudah membuat pipiku merona dan dadaku menghangat.
Jika sudah seperti itu, aku bingung dengan perasaanku.
Ia sendiri sepertinya paham dengan perasaanku. Tak pernah sekalipun ia terang-terangan mengamati jam tangannya jika sedang bersamaku. Ia hanya akan melakukannya jika kutanyakan tentang waktu. Aku sering mencuri lihat apakah di belakangku ia juga begitu, dan ternyata memang demikian adanya. Jika tak ada yang menanyakan, ia seakan tak menyadari keberadaan jam tangannya.
Kalau sudah begitu, aku akan jadi ‘orang ketiga’ yang sengaja bertanya: jam berapa?
Tak peduli tentang rasa apa yang berikutnya akan mendera. Ah, betapa bodohnya.
Semula, aku tak pernah ragu pada kemungkinan bisakah aku menggantikannya. Toh, secara genetik kami sama. Kepergiannya seakan menyeretku untuk menggantikan posisinya, yang dengan serta merta kuterima karena memang sejak lama aku mencintainya.
Ah, mestinya telah kusadari, bahwa—bahkan sejak awal—bukan aku yang dipilihnya.
Ah, betapa bodohnya.
Beberapa kali pernah terlintas di benak, untuk sekadar menggodanya, lalu mengubah putaran jarum di jam tangannya. Tapi memikirkan kemungkinan kemarahannya, niat itu tak pernah benar-benar terlaksana.
Biarlah, kupasrah pada waktu, jika memang berhenti padanya, aku bisa apa?
———
“Jam berapa?”
Aku mengangkat wajah dan melirik jam tanganku, “Setengah delapan. Lewat tiga menit.” Tak urung senyumku mengembang. Kuperiksa kembali benda melingkar itu, memastikan jawabanku tak keliru.
Dari sudut mata kulihat ia memperhatikanku. Kuangkat wajah dan tersenyum padanya. “Kita akan berangkat jam delapan, kau sudah siap?”
Ia hanya mengangguk pelan.
Kunjungan ke dokter kadang membuatnya senang, tapi tak jarang memukul kepercayaan dirinya. Jika sudah begitu, ia akan menjadi sosok asing itu. Secara fisik sama, tapi bisa kurasa berbeda.
Ah, seandainya waktu itu aku tak terlambat menjemputnya, ia akan pulang denganku, bukan menaiki taksi dan mengalami kecelakaan fatal yang merenggut kenangannya, yang sepanjang hidup kutahu berusaha ia isi kembali, —sayangnya—dengan sesuatu yang lain.
“Jam berapa?” ia bertanya lagi.
Aku mengangkat wajah. Ia sedang tersenyum padaku. Dia.
** selesai **

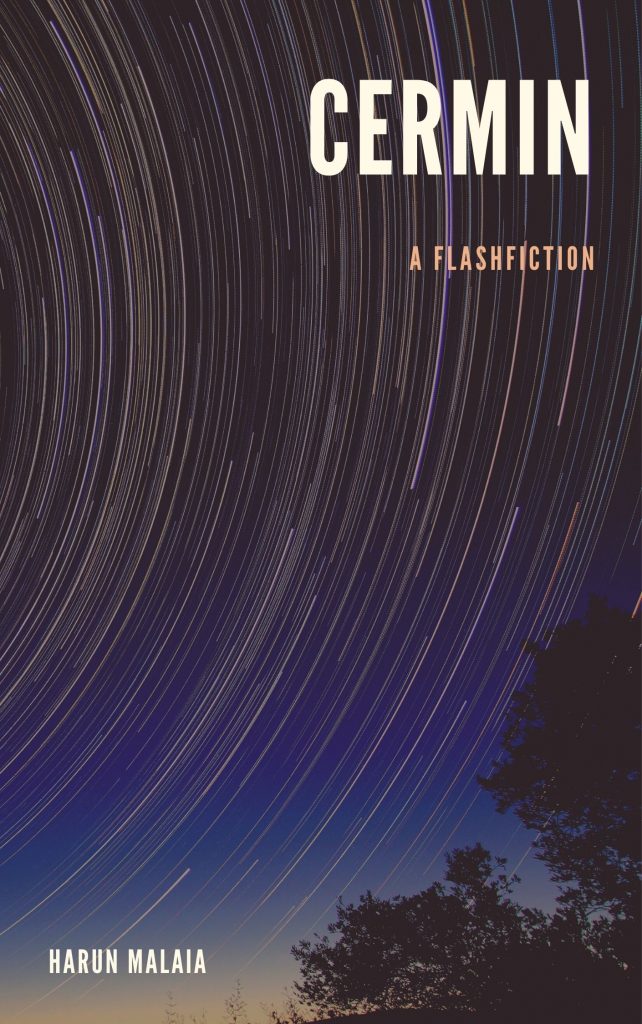

Tinggalkan Balasan