“Kau mau pergi?”
Desingan mesin jahit itu berhenti. Aku yakin wanita itu sedang menatapku sekarang. Tapi kubiarkan saja. Kuteruskan memakai kaus kakiku.
“Ada wawancara kerja.” jawabku datar.
Mesin jahit tadi kembali berdesing.
“Jam berapa kau akan pulang?”
Aku menarik nafas panjang. Kupakai sepatuku.
“Mungkin malam.”
Kembali suara desingan itu berhenti. Ekor mataku menangkap bahwa wanita itu bangkit dari belakang mejanya.
“Kau akan pergi sekarang?”
“Ya.”
“Sekarang?”
Rahangku mengeras. “Sebentar lagi.”
“Kau sudah sarapan? Mau kubuatkan kopi?”
“Aku akan makan di luar.”
Wanita itu memberikan sesuatu dari belakang pundakku. Sebuah payung.
“Belakangan ini sering hujan. Kemarin aku ke pasar dan membeli payung ini. Bisa dilipat. Kurasa bisa muat di dalam tasmu.”
Aku menerimanya. Memasukkannya ke dalam tas. Memang muat. “Terima kasih.”
“Aku akan membuatkanmu kopi. Akan kulihat juga jika masih ada roti.” Wanita itu memasuki dapur. Sekejap saja dia hilang di balik tirai.
Lengang.
Hanya suara gelas beradu dengan sendok logam.
Kusibak lengan kemeja panjangku. Mengintip arlojiku. Seharusnya Arman sudah datang delapan menit yang lalu.
Nah. Itu dia. Kulihat sepeda motor memasuki halaman. Arman membuka helmnya. Menekan klakson. Tersenyum padaku. “Assalamu’alaikum…”
“Wa’alaikumsalam. Kupikir kau tidak jadi datang.”
“Ah. Kau bisa saja. Jangan terlalu serius.” Arman memarkir motornya. “Kita berangkat sekarang?”
Aku terdiam. Kubalikkan tubuh. Memandang ke arah dapur. Hidungku mencium bau kopi dan roti bakar. “Ya. Aku akan ke dalam sebentar. Hanya sebentar.”
Aku bangkit berdiri dan memasuki dapur.
Wanita itu sedikit terkejut saat aku menyibak tirai. “Ternyata masih ada roti. Aku membuatkanmu roti bakar.”
“Arman sudah datang. Aku akan berangkat sekarang.”
Wanita itu terdiam. Ia menatapku lekat-lekat. “Rotinya memang belum siap. Tapi kopinya sudah bisa diminum.”
“Terima kasih. Tapi aku harus pergi sekarang.” Kusibak lengan kemejaku. “Aku bisa terlambat.”
Wanita itu tegak mematung. “Kau ingin membawa roti sebagai bekal? Kau belum sarapan.” suaranya terdengar bergetar.
“Tidak. Tidak perlu.” Aku menggeleng. “Aku akan makan di luar.”
Sesudah itu aku keluar. Wanita itu masih mematung.
*****
Hujan turun dengan deras. Aku bisa mendengar bunyi air yang memukul-mukul kaca jendela. Sepertinya akan lama.
Hujan yang lama.
Menunggu yang lama.
Seorang lelaki bertubuh besar berjalan melewatiku dengan tergesa-gesa. Ternyata namanya dipanggil. Ia menyenggol tasku. Dengan sedikit panik ia meminta maaf. Aku hanya mengangguk pelan. Membiarkannya lewat. Lalu mengambil tasku yang tergeletak di lantai.
Tanganku meraba sesuatu yang keras. Payung. Aku ingat aku membawa payung. Sepertinya tidak terlalu buruk membawa payung. Perasaanku jadi sedikit terganggu.
“Ibumu sendirian di rumah?” Arman menepuk pundakku. Membuatku tersadar.
“Ya.” Aku mengangguk pelan.
Ibumu sendirian di rumah? Hhh…
Ibuku sendirian di sana. Ibu kandungku sendirian di alam sana…
“Kulihat kau masih tidak berubah.”
Aku berpaling pada Arman. “Kau bicara padaku?”
“Kupikir kau harus memperbaiki komunikasi antara kalian berdua. Ia sudah bersamamu sejak lama. Tapi kau masih juga tak bisa menerimanya.”
Rahangku mengeras. Kutatap Arman lama. Tapi tak ada kata-kata yang keluar dari mulutku. Kerongkonganku terasa kering. Akhirnya aku berpaling. Menatap lantai.
Begitu mudah untuk kembali mengingat masa-masa pahit yang pernah terjadi. Seperti sekarang. Ketika langit pecah dengan hujannya. Siang menggigil dengan dinginnya. Manusia di sekitarku meringkuk pada kesibukannya. Pikiranku kembali ke masa silam. Aku masih tiga belas tahun saat itu…
“Ayah akan menikah lagi…”
Aku tidak menyatakan apa-apa. Yang jelas beberapa bulan kemudian aku mendapati seorang wanita telah resmi menjadi penghuni rumah yang selama ini kuhuni. Ibu tiri. Aku mendapatkan seorang ibu tiri.
Ibuku meninggal saat usiaku sepuluh tahun. Berarti telah tiga tahun berlalu. Namun tetap saja perasaan tidak senang muncul pada ibu tiriku itu. Meski setiap orang di keluargaku mengatakan bahwa ibu tiriku itu adalah seorang wanita yang sangat baik. Meski setiap orang menyatakan bahwa memang sudah saatnya ayah memiliki seorang pendamping hidup setelah tiga tahun ibu meninggal.
Aku lalu memutuskan masuk sekolah yang memiliki asrama. Kukatakan pada ayah bahwa aku ingin lebih mandiri. Tapi jauh dalam lubuk hatiku aku berteriak bahwa aku tidak sanggup melihat sosok ibu tiriku itu. Entahlah. Aku sangat ingin membencinya. Namun sayangnya, ia tepat seperti yang dikatakan keluargaku, dia wanita yang sangat baik. Tak ada alasan untuk membencinya.
“Kau takut Ayah melupakan Ibumu…?”
Ternyata Ayah menyadari perasaanku. Satu malam sebelum keberangkatanku ke asrama dia mengajakku bicara. Dari hati ke hati. Pembicaraan laki-laki.
“Ibumu adalah wanita yang hebat. Ayah tak kan pernah menyangkal itu. Dengarkan ini, simpan ini sebagai kata-kata yang bisa Ayah ucapkan sebagai penjelasan bagimu. Ayah sangat mencintai Ibumu. Sangat cinta. Dan Ayah tak akan pernah melupakan cinta itu. Bahkan seandainya Ayah berniat melupakannya, cinta yang terlalu dalam itu sendiri yang akan menuntut Ayah. Akan terus menuntut Ayah untuk mengingatnya. Di lain pihak, Ayah harus tetap hidup untuk beberapa waktu ke depan. Biarlah Ibumu menjadi penguat Ayah agar terus menjagamu. Karena cinta kami berdua seperti itu. Jauh di dalam lubuk hati ini Ayah menyimpan segala hal tentang Ibumu. Tidak akan pernah Ayah sia-siakan kenangan itu…”
“Muhammad Baihaqi…!”
“Kau dipanggil…” Arman kembali menepuk pundakku. Memutus lamunanku.
*****
Ayah meninggal sembilan tahun kemudian. Sekali lagi hatiku hancur. Apalagi saat aku melihat ibu tiriku terlihat begitu terguncang. Begitu sedih. Sebesar itukah cintanya pada ayahku? Aku sempat takut jika ibu masih hidup apakah akan terlihat sesedih itu. Aku takut jika ternyata cinta wanita itu jauh lebih besar daripada cinta yang telah ibu berikan pada Ayah. Ibu telah tiada. Tak ada lagi masa untuknya bisa menunjukkan perasaannya yang begitu halus. Sedang wanita itu dengan bebas bisa mengekspresikan cintanya.
Sepeninggal Ayah aku bingung akan terus hidup sendiri ataukah kembali ke rumah. Keluarga yang lain mengatakan sebaiknya aku kembali ke rumah saja. Karena sekarang ibu tiriku sendirian. Ia tidak memiliki anak. Baguslah. Aku bakalan lebih senewen jika ternyata ia memiliki anak. Aku menurutinya. Tinggal bersama wanita itu.
Dan selama kami — aku dan ibu tiriku — tinggal bersama itulah aku melihat dengan jelas apa yang dimaksud dengan ‘kebaikan’ wanita itu. Pantas jika ayah memilihnya menggantikan ibu. Sekali lagi aku gugup jika seandainya ibu dan wanita itu harus bersaing memperebutkan ayah, aku tidak begitu yakin dengan hasilnya.
Lambat laun aku mulai menerima ibu tiriku itu. Paling tidak aku menghargainya. Ia wanita yang baik. Sholehah. Ia menutup dirinya dengan baik. Ia menjaga kehormatannya dengan baik.
Sebentar.
Kurasa aku lupa mengatakan tentang satu hal. Satu hal yang sangat penting. Cerita ini takkan jelas tanpa sesuatu itu.
Ibu tiriku itu masih muda.
Ia menikah dengan ayahku saat berumur sembilan belas tahun.
Aku harus mengakui tidak terlalu nyaman tinggal bersamanya. Aku harus berusaha menumbuhkan kebencian — paling tidak rasa tidak suka — padanya. Sebab ternyata aku mulai menyukainya. Menyayanginya. Ingin menjaganya.
Aku tahu perasaan itu tidak bisa dibenarkan. Sama sekali tidak bisa dibenarkan. Karena itu perasaan sayang itu tak boleh kubiarkan tumbuh dengan bebas dalam hatiku. Aku menyimpan rapat-rapat perasaanku itu. Aku harus memupuk benci agar perasaanku pada wanita itu tidak menjadi perasaan yang tak terkendali. Tidak terlalu menyenangkan bersikap seperti itu. Tapi aku membiasakannya. Seperti tadi pagi. Benar-benar tidak nyaman. Jauh di dalam lubuk hatiku aku ingin tahu seperti apa perasaannya terhadapku.
“Mas. Sudah mau tutup…”
Aku membayar makananku. Beranjak dari dudukku.
Hujan belum reda. Benar-benar lama. Meski sekarang sudah tidak sederas tadi. Kurapatkan jaketku. Mencoba mengusir dingin. Mengusir pikiran-pikiran liar yang sedari tadi mengisi kepalaku.
Aku pulang sendirian. Arman berpisah denganku sejak Asar. Sekarang sudah jam sebelas. Jalanan sudah mulai lengang. Lengkap sudah sketsa buram malam ini. Sendiri. Sepi. Dingin. Beku.
Aku memutuskan untuk pulang dengan jalan kaki saja.
Kubuka payungku. Mulai berjalan pulang.
“Maaf. Bisa beritahu saya di mana jalan Beringin?” seseorang menyela jalanku.
Seorang gadis. Usianya pasti di bawahku. Memakai jas hujan yang menutupi kepalanya. Kerudungnya tepatnya. Mengingatkanku pada wanita itu.
“Sudah dekat. Di ujung belok kiri saja.”
Gadis itu mengikuti arah telunjukku. Wajahnya menyiratkan kelelahan. “Terima kasih.”
Aku terdiam. Mengamatinya. “Terima kasih kembali.”
Gadis itu sudah menjauh. Menarik travel bagnya. Selain itu ia juga membawa beberapa tas gendong. Kelihatannya berat.
Aku mengejarnya. Mempercepat langkahku. Bisa kulihat ia sedikit terkejut saat melihatku lagi.
“Kupikir kau perlu bantuan…”
*****
Aku tiba di rumah lewat tengah malam. Rumah kosong. Kemana wanita itu?
Diam-diam aku merasa cemas.
Sampai kutemukan sebuah surat terletak di atas meja makan.
Assalamu’alaikum.
Anakku. Izinkan aku memanggilmu demikian.
Aku pergi ke Panti. Mungkin akan tinggal di sana lagi. Maaf jika aku melakukan ini. Tadi siang saat kau menelepon meminta dilihatkan berkas-berkas surat, aku terpaksa mencarinya di kamarmu. Dari sanalah aku menemukan alasan mengapa aku harus melakukan ini. Kupikir akan jauh lebih baik jika aku pergi.
Anakku. Biar bagaimanapun kau tetap adalah anakku. Aku adalah istri ayahmu. Aku mencintai ayahmu. Jika yang tersisa darinya adalah kau, maka aku juga menyayangimu, sebagai seorang anak dari suamiku. Aku menyayangimu seperti itu.
Anakku. Aku akhirnya mengerti mengapa selama ini kau bersikap dingin padaku. Kau menulis dengan sangat jelas dalam buku harianmu. Terima kasih karena sudah dengan sepenuh hati menjagaku. Aku sangat menghargainya.
Anakku. Kau adalah laki-laki yang baik. Darah ayahmu mengalir dalam darahmu. Aku percaya kau akan segera menemukan cinta lain yang bisa kau jaga dengan kebaikan hatimu, jauh lebih kuat dari saat kau menjagaku. Aku sangat percaya itu.
Aku minta maaf atas kesalahanku selama ini. Aku mendoakanmu untuk seluruh kebahagiaan yang ada di atas dunia ini. Kau pantas menerimanya.
Sekali lagi maafkan aku.
Ratih
Kulipat kembali surat itu. Meletakkannya ke atas meja. Kurasakan tubuhku menyerah. Kutarik sebuah kursi untuk kemudian mendudukinya. Kepalaku terasa berdenyut.
Perlahan aku bangkit. Menuju kamar wanita itu. Ibu tiriku. Ia benar-benar sudah pergi.
Aku beralih ke kamarku. Mataku langsung menangkap buku harianku tergeletak di atas tempat tidur. Aku ingat aku tidak meletakkannya di sana. Sepertinya wanita itu memang membacanya.
Malam itu aku benar-benar sendirian.
Wanita itu benar-benar pergi.
***** selesai *****

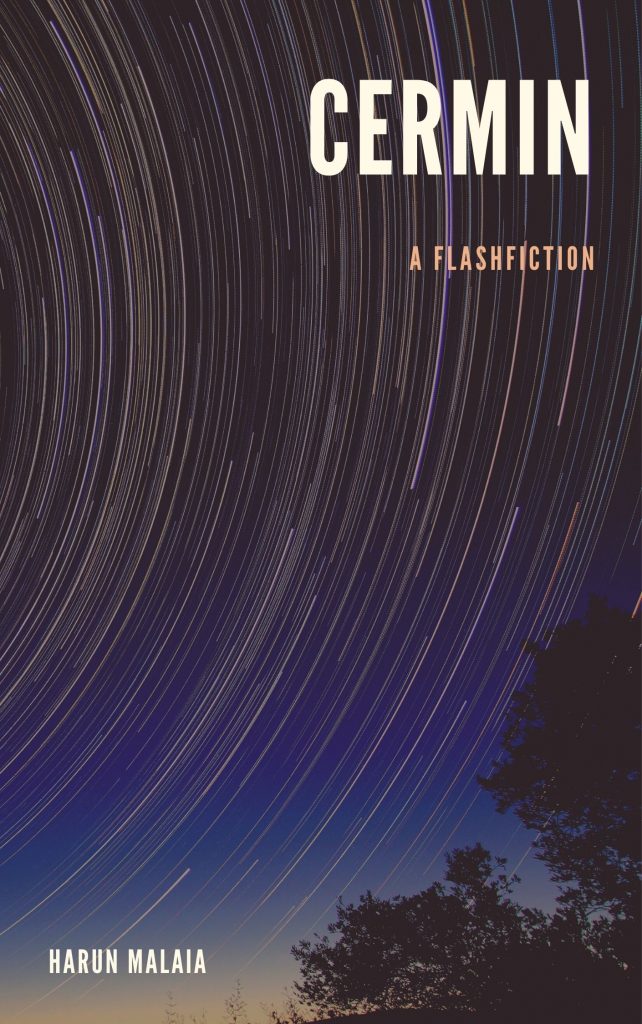

Tinggalkan Balasan