MENDUNG menggelayut rendah di tepian langit. Angin berembus semilir, cukup untuk menggoyangkan kuntum-kuntum kemboja yang mulai layu sore itu. Pekuburan lengang selayaknya tempat peristirahatan terakhir orang mati.
Sampai sedan putih dengan ban berdecit itu datang.
Seorang wanita separuh baya berpakaian serba hitam keluar dengan tergesa. Sendirian. Tangannya merogoh bergantian ke dalam saku mantel panjangnya seakan mencari sesuatu sedangkan langkahnya masih secepat mobilnya datang.
Dia menemukan apa yang ingin dicari. Langkahnya terhenti.
Wanita itu menegakkan leher dan menarik napas dalam sebelum membuka kacamata hitamnya. Untuk sesaat pekuburan kembali lengang, wanita itu masih mematung. Hanya pandangannya yang menyapu sekitar. Tadi tangannya, kini matanya.
Mencari sesuatu.
Kemudian kembali dia melangkah, kali ini pelan. Terlalu pelan, untuk ukuran betisnya yang jenjang. Tiba di nisan tujuan, dia berhenti dan kembali menarik napas panjang.
Pekuburan kembali lengang. Kuntum kemboja kembali bergoyang.
“Hai,” wanita itu menelan ludah, “ini aku.”
*****
25.
Dia membakar dua lilin tersebut dengan hati-hati. Meletakkannya di atas batu datar yang banyak berserakan—pernah satu kali dia ingin meletakkannya di atas nisan tapi pikiran bahwa dia membakar kepala orang mati mengganggunya. Terlebih lagi, ini bukan sembarang orang. Ditariknya napas panjang sebelum lirih berkata, “Selamat ulang tahun. Kelahiranmu. Kematianku.
Aku minta maaf karena hanya datang sekali setahun. Ini tak pernah mudah, meski sudah sekian lama. Berbeda dengan kebanyakan orang yang berkabung, setiap hari yang berlalu justru semakin berat bagiku.
Terlebih hari ini.
Namun, aku telah berjanji akan datang jadi di sinilah aku. Menemanimu. Maaf karena datang sendirian. Karena pria yang seharusnya menemaniku seumur hidup sepanjang hayat, apalah namanya—membatalkan pertunangannya denganku hari ini.
Mungkin orang bilang lebih baik gagal menikah daripada bercerai. Benarkah demikian?
Kautahu aku belum pernah menikah, jadi tak bisa tahu tentang itu. Tak menikah berarti tak bisa punya anak. Aku tak mau punya anak tanpa ada suami.
Kautahu benar itu.”
Wanita itu merapikan rambutnya yang tertiup angin. Sempat dia memindahkan posisi lilin, melindunginya agar tak padam, meski tindakan itu dirasakannya konyol, seperti menjaga lilin babi. Akan tetapi dilakukannya juga. Selepas itu dia menyeka hidungnya yang beringus, lalu kembali bicara, kali ini lebih lancar dan santai.
“Saat aku membeli lilin, si penjual bertanya untuk siapa aku membeli lilin. Kukatakan saja, untuk mantan pacarku yang selamanya berusia dua puluh lima.
Bukankah seharusnya dua lima itu melambangkan kebijaksanaan? Nabi menikah saat usia dua puluh lima, kan? Jangan salah, aku tidak sedang membandingkan dia dengan nabi. Astaga. Dunia langsung kiamat jika dia seorang nabi.”
Wanita itu tersenyum. Kembali menghapus ingus.
“Aku merindukanmu. Bukankah itu aneh? Merindukan sosok yang bahkan tak pernah ada. Bisakah rindu membuatmu gila? Semoga tidak. Mencari suami saat waras saja sudah susah setengah mati. Ya, ya… aku masih berharap menemukan suami meski baru ditinggal pergi.
Ah.
Aku merindukanmu. Sungguh. Aku sering berandai-andai jika kita berdua tumbuh dewasa bersamaan. Kau dan aku. Kita bisa jadi teman baik, bukan? Aku melihat masa kanakmu. Kau melihatku. Mungkin saja aku akan tumbuh jadi orang yang berbeda, dan kau tak akan ada di sini, dipasangi lilin setiap tahun oleh wanita yang tidak gadis, tetapi bukan pula janda.
Ibu dan anak, menua bersama. Mendengarnya saja romantis.
Kautahu, sepanjang tahun aku memikirkan apa saja yang ingin kubicarakan denganmu jika kita bertemu. Hai. Hello. Apa kabarmu? Aku takut terlihat gila jika bicara sendiri, makanya kubawa kitab suci. Setidaknya aku terlihat sedang mengaji.
Sebenarnya mana yang lebih kauperlukan? Obrolanku? Atau surat-surat di kitab ini?”
Senja mulai turun tetapi wanita itu belum selesai. Dia kini duduk bersimpuh, menepuk-nepuk gundukan di depannya dengan tangan yang tak memegang kitab.
“Aku berharap kedatanganku tidak memberatkanmu. Peziarah harusnya jadi penawar luka, bukan? Mantan pacarku pernah mengunggah fotonya saat sedang berziarah—bukan ke kuburanmu tentu saja, dan dia sangat bergaya di sana. Maksudku, itu normal sekarang. Bergaya di kuburan. Aku tak pernah bisa melakukannya. Jika kau bisa melihatku sekarang, aku benar-benar kacau. Hitam. Serupa gagak pemakan bangkai.
Apakah gagak akan memakan bangkai anaknya sendiri?
Seperti biasa, aku merasa kau akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan konyolku. Aku merasa, jika saja kau terus hidup, akan jauh lebih bijaksana daripada aku yang konyol ini.
Bicara tentang bijaksana, aku ingin cerita tentang perjalananku hari ini. Selepas putus dengan mantanku, aku terniat untuk lompat dari jembatan. Bukan karena ingin mati—seseorang yang hatinya sudah mati tak butuh bunuh diri—, tetapi karena aku lelah dan bosan. Mungkin lain waktu akan kupertimbangkan bungee jumping. Rasanya pasti menyenangkan; jatuh tetapi tahu pasti akan ada yang menahan. Serapuh apapun tali yang memegang betisku nanti, setidaknya aku tahu tak sendirian.
Menurutmu, apa aku sudah layak untuk mati?
Atau, mantanku itu, mungkin dia belum layak mati, tetapi apa yang paling baik aku doakan untuknya? Jelas aku tak mendoakan kebahagiaan. Brengsek sekali. Dia memang sudah brengsek sejak lama, tapi setidaknya belum memutuskan aku seperti hari ini. Lama-lama terpikir kalau aku memang pantas untuk jatuh dari jembatan, bukan sebagai manusia, tapi sampah—atau percikan kotoran gigi yang ikut keluar saat seseorang meludah keluar jendela.”
Wanita itu berhenti bicara. Sebagai ganti dia menarik sepucuk surat usang dari sakunya.
Maafkan aku.
Setiap tahun aku akan meminta maaf padamu. Berharap Tuhan mengampuniku.
Aku berpikiran pendek, hanya ingin senang. Nyatanya aku menyesal sekarang. Sesal selalu datang belakangan dan tak ada yang bisa kulakukan kecuali meratapi keputusan buruk itu.
Aku menyesal tak menyadari datangnya cinta di hatiku. Bahkan sejak di dalam rahim, aku ternyata telah jatuh cinta padamu.
Aku meninggalkanmu karena tak punya suami. Kuulangi lagi ini setiap tahun, agar kau memaafkanku. Seorang wanita bisa tolol melebihi hewan jika hamil sendiri. Tentu saja aku tak seberuntung Maryam,—jika kita menganggap Maryam beruntung, karena saat Isa lahir, orang juga berpikiran kotor tentangnya dan itu sama sekali tidak beruntung. Mereka tidak tahu saja siapa Isa.
Wanita itu memejamkan mata. Lilinnya telah padam. Habis ditelan api. Tinggal sumbunya yang kini serupa abu.
Pada gundukan dan nisan di depannya, dia kembali bicara.
“Dua puluh lima. Itu usiamu sekarang, seandainya malam laknat itu tidak kulakukan apa yang telah kulakukan. Mati berkali-kali pun tak bisa aku menebus nyawamu yang kucampakkan. Satu yang selalu kuminta, bertemu denganmu.
Hanya satu. Tak pernah bisa.
Lalu bisakah cinta yang datang terlambat, tiba di pangkuanmu tepat waktu?”
******

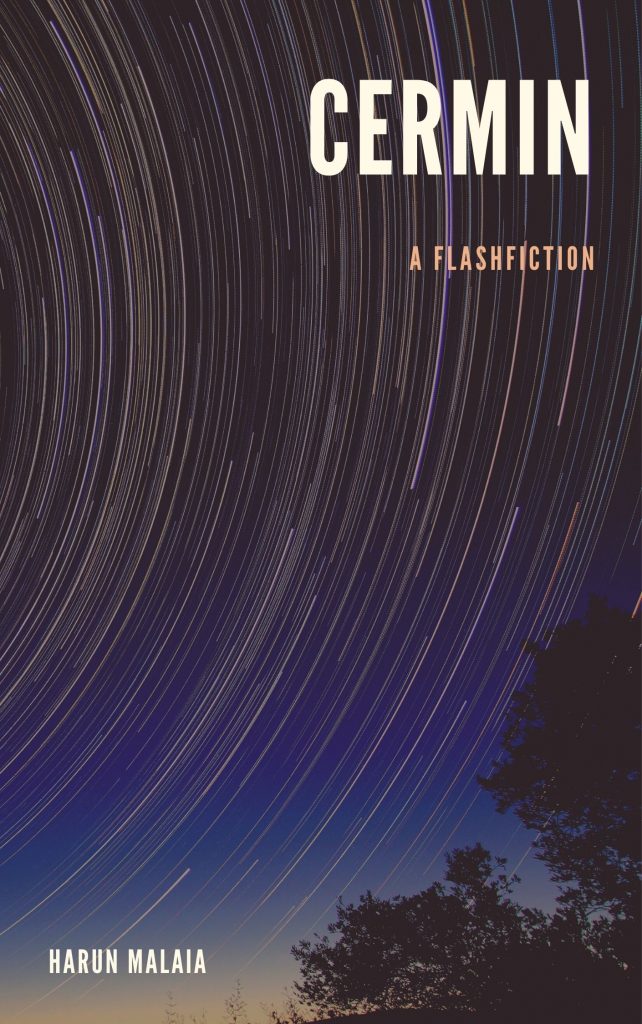

Tinggalkan Balasan