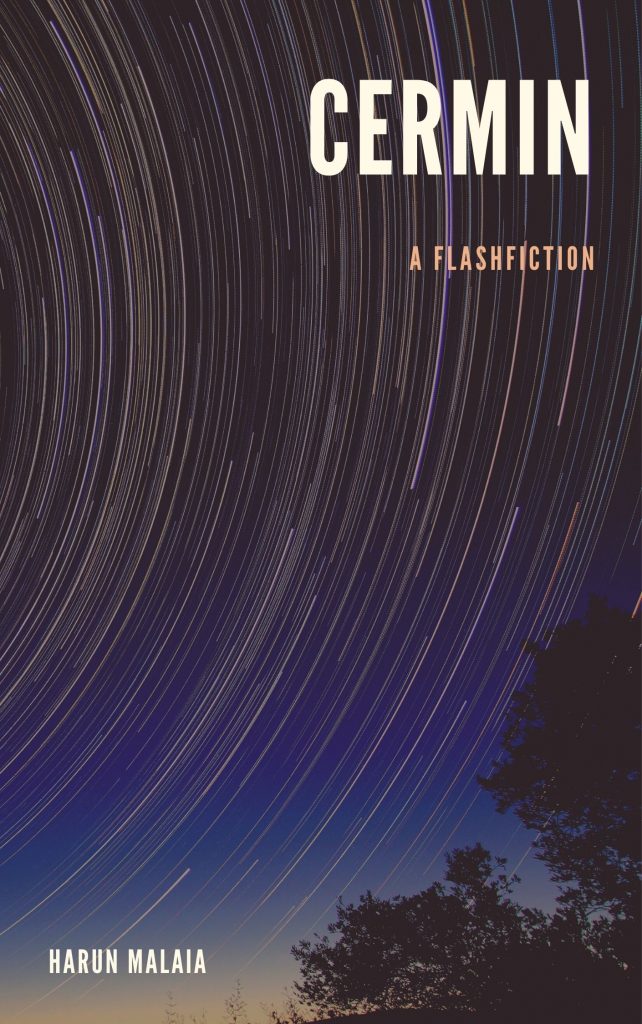Penulis: Harun Malaia
-

Kau terbangun dengan sentakan yang menyakitkan. Alih-alih beristirahat dengan tenang, belakangan ini tidur telah menjadi momok yang menakutkan. Dua bulan terakhir, tepatnya. Ya, kau yakin persis karena sejak mimpi itu berulang, kau telah menandai angka-angka di kalender dengan spidol merah. Silang berarti mimpi buruk; lingkaran berarti tidak adanya mimpi — atau tidak tidur sama sekali.…
-
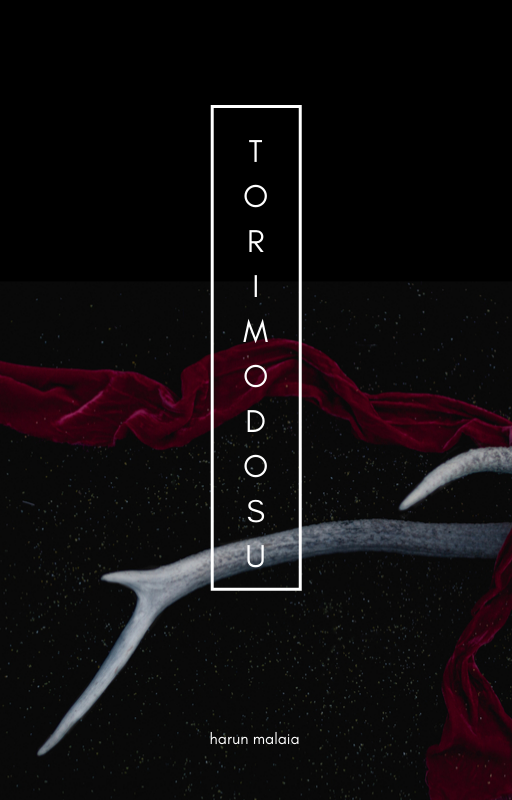
Hana menghela napas dalam. Disekanya keringat yang mengalir di kening. Siang itu terik. Ditambah lagi ia harus berdesakan di dalam angkot. Seorang bapak separuh baya tampak tenang mengisap rokok, untuk kemudian dengan lebih tenang mengembuskannya keluar. Hana menghela napas lebih dalam. Dadanya sesak tak tertahankan. Maka ketika ia melihat persimpangan jalan menuju rumahnya, ia buru-buru…
-

“Meltendera Stonia…!!” Dari sekian banyak peruntungan yang ada di dunia Gar, ini nasib terburuk bagi para gargoyle. Sedari awal, pencampuran biji Oak yang tak genap berusia 243 hari membuatku tak sempurna. Alih-alih sayap, sepasang tulang mirip tanduk bergelambir yang justru tumbuh di tempat seharusnya sayapku berada. Jika saja kutemukan kurcaci laknat yang melakukan pencampuran keliru…
-
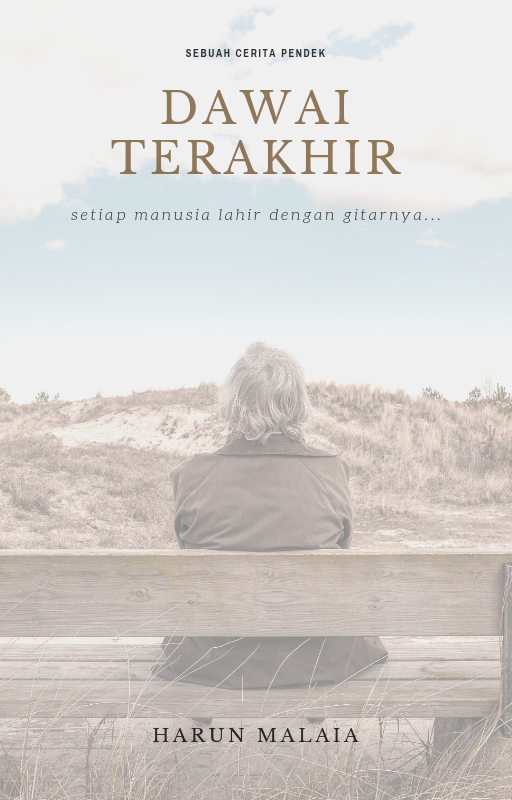
Jika normalnya seorang bayi lahir akan menangis dan beberapa menit kemudian tembuninya keluar, maka tidak dengan Kakek. Setidaknya begitu yang kudengar dari cerita turun-temurun keluarga yang kerap diulang Ibu padaku. “Kakek lahir, dan langsung bernyanyi bersama gitarnya.” Dulu, aku selalu mencibir dan mencemooh cerita itu, sampai kemudian kakek tinggal bersama kami, tepatnya dua bulan yang…
-

“Astaga, kau lihat si Petunia? Dia sudah berkotek-kotek lagi!” Oklahoma berhenti mengais-ngais dan memiringkan kepalanya. Mempertimbangkan kata-katanya sebelum berucap; dia tahu Esther hanya sedang ingin bergosip, “Bukankah baru minggu lalu dia selesai mengeram?” “Itu maksudku! Betina itu hanya pandai berbuat tapi coba kau lihat apa hasilnya. Hampir semua anaknya mati lumpuh layu!” “Saat itu sebenarnya…