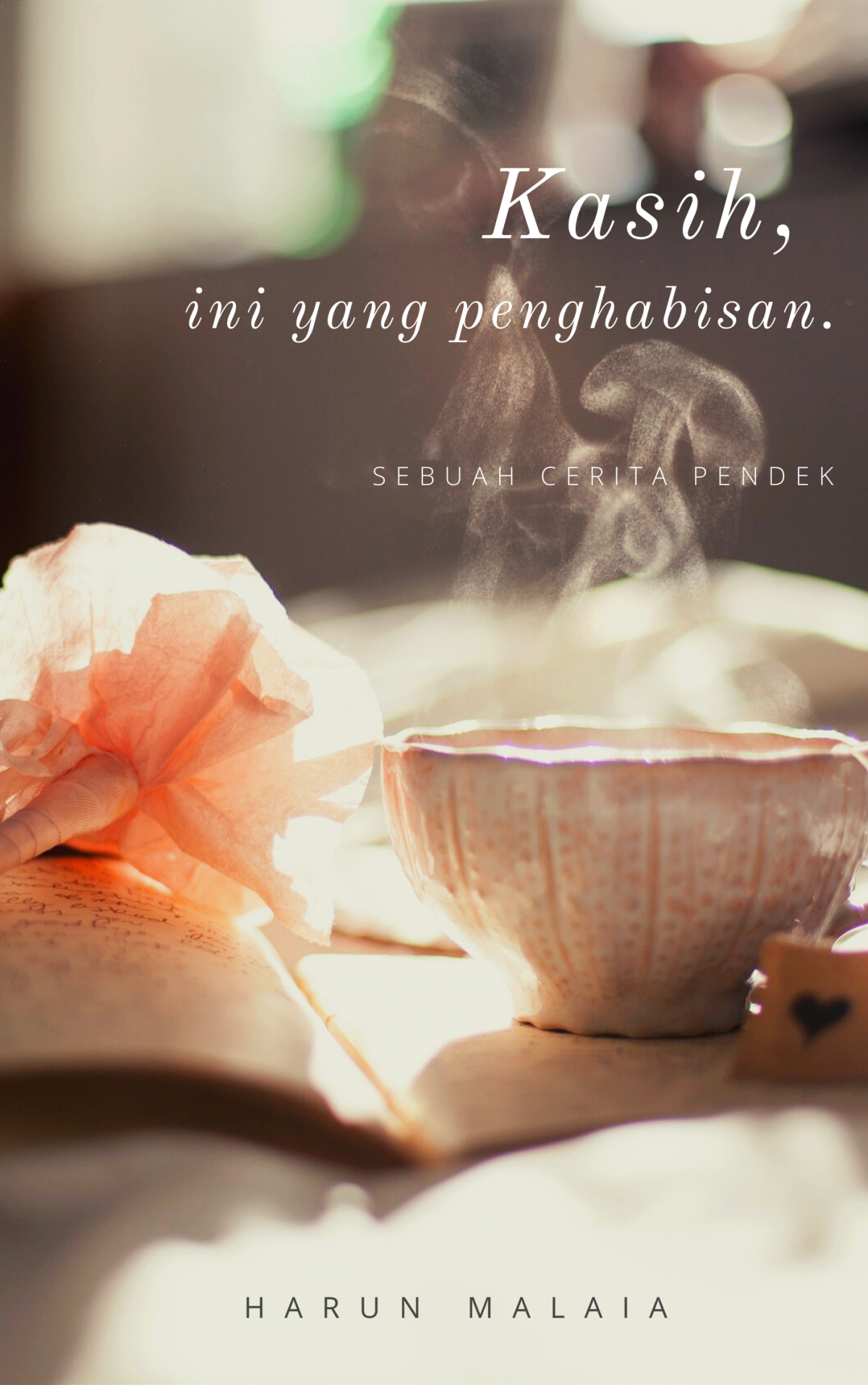Apa yang lebih berat daripada terus menerus mengingatmu?
Terpaksa aku.
Dalam tiap rinai yang basah.
Aku gelisah.
Tak ayal lagi rindu yang membuncah.
Pecah tak berkesudah.
Di bawah hujan sore itu.
Waktu seakan tak pernah berlalu.
Hanya ada kau… lalu aku.
(1)
Adam menepikan sepeda motor dengan tergesa. Bersungut-sungut dia memaki dalam hati. Joni, abangnya yang pelupa, pasti tidak langsung mengembalikan jas hujan ke dalam jok motor. Beberapa orang siswa lain juga memilih untuk berteduh. Hujan deras turun tiba-tiba beberapa saat setelah pagar sekolah dibuka. Melihat tebalnya awan yang sekarang menggelayut di langit, hujan ini akan lama.
Seorang siswi berlari tergesa dan mengambil tempat berdiri persis di sebelah Adam; siswi itu sedang menelepon. Adam bisa melihat pakaiannya sudah setengah basah. Butir-butir air hujan tampak jelas di lengannya yang sedang melekatkan handphone di telinga, mengalir pelan dan menetes jatuh setelah sempat berkumpul sebentar di bagian sikunya.
“Ya, Mama. Aku masih terjebak hujan.”
Adam tersenyum, dia mengenali siswi di sampingnya sebagai siswi baru di kelasnya. Suaranya terdengar berbeda dari jarak sedekat ini.
Merasa diperhatikan, siswi itu memalingkan wajah, lalu tersenyum sambil menyapa, “Hai.”
Adam sampai tergagap, “Hai. Kau ingat aku? Kita sekelas.”
Siswi itu masih tersenyum. “Ya, kau yang dihukum karena tidak membuat tugas Fisika.”
Adam bisa merasakan darah mengalir deras ke daerah kepalanya, “Ah, kini aku berharap kau tak mengingat apa pun.”
Siswi itu tertawa. Memperlihatkan deretan gigi yang rapi luar biasa, “Kau juga ketua kelas.”
Adam hanya mengangguk-angguk pelan, “Kau boleh mengingat yang itu,” dia kemudian memaksa dirinya untuk tersenyum. Digesernya posisi berdirinya agar lebih mendekat, “bagaimana hari pertamamu? Dan maafkan aku, namamu Ana, bukan?”
Siswi bernama Ana itu mengangguk pelan. Dengan tangan kirinya dia menyisipkan helai-helai rambut yang berkibar tertiup angin ke belakang telinganya. “Kau — Adam?” dia sempat mencuri lihat pada badge name yang terjahit di seragam Adam. “Tadi apa pertanyaanmu?”
Adam menggaruk kepalanya, “Bagaimana hari pertamamu? Kuharap tidak mengecewakan.”
Ana menggeleng. Membuat rambutnya kembali jatuh ke sisi wajahnya. Adam memperhatikan saat dia kembali menelusupkannya ke belakang telinga. “Untuk hari pertama, kau tidak akan mendengar keluhanku.”
“Baguslah,” Adam mengangguk, “aku senang mendengarnya.”
Ana berpaling padanya, “Benarkah? Wajahmu tidak terlihat senang.”
“Ah,” Adam kembali merasakan wajahnya panas. Dia lalu menceritakan tentang jas hujannya yang dipinjam oleh abangnya. “Biasanya kalau pakai jas hujan, aku bisa menembus hujan.”
“Menembus hujan?”
Adam berpaling, “Ya.”
“Kau menggunakan pilihan kata yang jarang kudengar,” Ana tertawa pelan. Entah kenapa Adam senang mendengarnya, dia jadi bersemangat untuk bercerita lebih banyak.
“Aku senang merasakan hujan jatuh di atas jas hujanku saat di atas motor. Bisingnya menenangkan.” Adam merapatkan tangannya, memeluk dada. “Kau sendiri?”
Ana menggeleng pelan sambil tersenyum, rambutnya kembali tergerai. Kali ini dia mengumpulkan mereka semua di sisi bahu kanannya. Dari sudut matanya, Adam bisa melihat kulit leher di bawah telinganya sekarang. “Aku menderita asma,” sambung Ana.
Adam menunjukkan wajah khawatir. “Sekarang kau tidak apa-apa?”
“Aku baik-baik saja.”
“Kau yakin?”
Ana memiringkan kepala, berpaling pada Adam, “Apa tugas ketua kelasmu sampai sejauh ini?”
Adam tak mengerti, jelas itu tergambar di wajahnya karena Ana kembali tertawa sebelum akhirnya berkata, “Kau sangat perhatian.”
Adam belum pernah merasakan wajahnya sepanas itu.
*****
Berdua kita pernah menyandarkan hati
menatap langit dan menunjuk bintang yang sama
berdua kita pernah menguatkan diri
ketika semua sulit dan gelap membayangi
padamu aku percaya
padaku kau percaya
berdua sudah cukup
kau alasan bagiku untuk bahagia
(231)
“Kau tidur berapa jam?”
Adam mengangkat wajah, mengangkat bahu tak acuh. “Tidurku cukup.”
Ana menatap Adam cukup lama, seakan memastikan kata-kata terakhirnya itu dapat dipercaya. Dia kemudian mengangsurkan beberapa lembar kertas, “Aku suka bagian yang ini. Meski kurasa kau kadang lepas kontrol.”
“Lepas kontrol?”
“Kau memasukkan keinginanmu ke dalam kisah ini.”
“Bukankah aku yang menulisnya? Aku bisa saja memasukkan apa yang kuinginkan.”
Ana menggeleng pelan, “Ini sedikit terlalu banyak. Tidak sesuai dengan watak tokoh yang kautulis.”
Adam mencibir, “Sedikit terlalu banyak.”
“Terserah kau saja berarti.”
Adam menopangkan dagu pada telapak tangan kiri sementara dengan tangan kanan dia mengaduk teh yang baru saja diantar. Dilihatnya Ana mengambil beberapa lembar kertas dan mulai menggambar.
“Aku tidur satu jam saja,” Adam membuka suara.
Ana tidak menjawab. Dia masih saja menggambar.
“Belakangan ini aku terus memikirkanmu, Ana.”
Adam melihat Ana terus menggambar. Ia kemudian mengangkat gelasnya dan meminumnya beberapa teguk. Hangatnya langsung membuat hidungnya terasa penuh.
“Aku tahu kau tidak menyukaiku sebanyak aku menyukaimu.”
Gerakan tangan Ana terhenti.
Dia mengangkat wajah.
Pandangan mereka bertemu.
“Aku mengerti keadaanmu sekarang, tetapi aku tidak bisa menahan perasaanku sendiri,” lanjut Adam tergesa.
Ana meletakkan pensilnya. Menggerakkan tangan ke arah telinga, untuk kemudian menariknya kembali.
Adam mendengus pelan.
Kini tak ada lagi anak rambut berjatuhan di pipi. Tidak ada lagi gerakan semi otomatis menyelipkan rambut di belakang telinga. Tidak ada lagi pemandangan kulit leher yang tersembunyi.
“Kau ingin mengatakan apa?” suara Ana terdengar bergetar.
Adam berdehem pelan, kerongkongannya tercekat. “Ini terakhir kalinya aku meminta padamu. Jika kau tidak bisa bersamaku, pacaran denganku, kurasa akan lebih baik jika kita tidak bertemu sama sekali.”
“Kita sekelas.”
“Kau bisa menghindariku. Atau sebaliknya.”
“Sebegitu mengganggu perasaanmu?”
Adam mendengus dan memaki pelan.
Ana menarik napas dalam dan mengemasi tasnya. Adam mencoba menahannya.
“Ana…” Adam tercekat saat mengucapkan nama itu.
Ana menatapnya sejenak, lalu memasukkan pensil dan kertasnya. Dia juga mengangsurkan kembali naskah yang tadi malam dia edit. “Aku pergi.” Dia kemudian berdiri dan keluar dari belakang meja. Saat membuka pintu kafe, udara panas di luar yang berangin menyambutnya, mengibarkan kerudungnya.
*****
karena kata yang telah terucap tak dapat ditarik kembali
begitu juga dengan kepergianmu
yang membawa serta mimpiku
kau segala yang kutahu
harus darimana aku memulai lagi?
karena hidup adalah tentang pembelajaran
meski semua tak kutahu bisa sesakit ini
kehilangan
(298)
“Ada apa? Bingkisan apa ini?” tanya Ana, setengah berteriak.
Adam mengedikkan kepala, mengajak Ana keluar ruangan yang penuh dengan siswa berpakaian gelap. Sekarang malam perpisahan SMA. Musik berdentam-dentam menulikan telinga dari setiap sudut ruangan. Namun tak seorang pun yang benar-benar memedulikannya, semua tampak asyik dengan kegiatannya sendiri. Beberapa tampak berfoto bersama, mencoba untuk membuat kenangan untuk terakhir kalinya. Sebagian bercerita dengan suara keras agar terdengar dengan lawan bicaranya, saling menceritakan penggalan-penggalan kisah yang sempat terjalin antara mereka semua. Terutama yang menyenangkan. Tawa biasanya sudah pecah bahkan sebelum kisah selesai diceritakan.
Ana mengikuti langkah Adam keluar ruangan. Meski tetap saja ramai, paling tidak kalau bicara tidak perlu sambil berteriak.
“Di sini saja.” Ana berhenti melangkah.
Mereka sekarang di salah satu sudut yang hanya berisikan sekelompok siswi yang saling bercerita sambil bergantian berfoto.
Adam berbalik dan sekarang mereka berhadapan.
Adam menunjuk pada bingkisan yang tadi ia berikan pada Ana. “Itu buku. Aku biasa menulis di sana.”
“Lalu?”
Adam tampak gelisah. Ana mengenali tanda-tandanya. Dia berulang kali menjejak dengan ujung sepatunya, bergoyang-goyang kecil. Kedua tangannya juga dimasukkan ke dalam saku celana.
“Kupikir aku tidak akan menulis lagi.”
Ana berdecak, “Adam, apa sebenarnya yang ingin kau katakan?”
“Aku tidak ingin menulis lagi.”
“Apa?”
“Aku tidak bisa menulis lagi!”
Ana mengerutkan kening, menatap Adam tajam, “Adam, aku tidak tahu kenapa kau tiba-tiba membicarakan ini. Terakhir kali, kau mengatakan tidak ingin bicara lagi denganku. Sekarang kau memberikan aku buku dan mengatakan kau tidak akan menulis lagi.”
Beberapa siswa yang tadi asyik berfoto dapat mendengar nada suara Ana yang mulai meninggi. Mereka sekarang mulai memperhatikan. Adam yang menyadari hal itu lalu menarik tangan Ana melangkah menjauh.
Gerakannya itu membuat Ana terkejut.
“Hei!”
Adam membawanya ke depan gedung sekolah. Menuruni tangga. Menuju parkiran.
“Adam. Lepaskan aku.”
“Kita bicara di mobil.”
“Aku tidak bisa hanya berdua denganmu.”
Adam memaki pelan. Dilepaskannya tangan Ana.
Sekarang mereka memang hanya berdua di area parkiran.
“Itu yang tidak kusuka darimu. Kau pikir aku akan melakukan apa? Hah?!” suara Adam sampai menggema saking kerasnya dia berteriak. “Aku tahu kau sekarang sudah menggunakan jilbab. Atau kerudung. Atau apa pun istilahnya. Aku tahu kau sekarang tidak lagi bergaul bersama siswa laki-laki. Aku berterima kasih karena setelah semua itu terjadi kau masih mau membaca tulisanku. Kau masih mau bertemu denganku. Kau membuatku merasa bahwa aku istimewa di matamu. Tapi kau harus tahu bahwa aku benar-benar sayang padamu dan aku tidak sama sekali berniat untuk merusakmu.”
“Kau sudah pernah mengatakan ini.”
“Oh, Ana… kau membuatku gila.”
“Adam. Kau tidak perlu berteriak.”
Adam mengangkat tangannya, meminta maaf. “Aku tidak akan berteriak.”
Ana menarik nafas panjang. Dia menimang-nimang buku di tangannya. “Jika kau memintaku untuk kembali bersamamu, aku tidak bisa.”
“Ana…”
“Aku akan menerimamu jika kau ingin menikahiku.”
Adam terperangah, “Kau gila? Bagaimana bisa aku menikahimu?”
“Karena kita baru saja lulus SMA?”
“Karena kita baru saja lulus SMA. Karena aku tidak bekerja. Karena aku hanya menginginkan kau bisa lebih lama bersamaku. Menemaniku menulis. Mengajakku bicara. Aku tidak akan melakukan lebih. Aku bersumpah. Aku belum siap menikah. Kau belum siap menikah,” Adam gelagapan.
“Aku akan menerimamu jika kau ingin menikahiku.”
Adam menggeleng-geleng pelan. Dia bersandar pada mobilnya. Saat mengangkat wajahnya lagi, matanya berkaca-kaca. Ditatapnya Ana sambil berucap pelan, tangannya terangkat seakan meminta penjelasan, “Bagaimana bisa kau melakukan ini padaku?”
*****
jauh di dalam sana
kau ada
tidak perlu susah payah
untuk mengingat semua kisah
bahkan kehancuran pun bisa terasa indah
melihatmu lagi
aku seperti pernah mengenal getir ini
(4376)
“Ah… aku tidak pernah suka hujan seperti ini,” Rani merapatkan jaket yang dia kenakan, “Bisakah kita kembali ke dalam? Jika kita pulang sekarang kemungkinan jalan juga akan macet dan kau tahu aku tidak senang berdiam diri di mobil dalam cuaca seperti ini.”
Yang diajak bicara malah beranjak menuruni undakan tangga, tepat berhenti di batas lantai yang terkena tempias air yang tertiup angin sore itu. Laki-laki itu mengulurkan tangan dan merasakan butiran-butiran air yang lembut langsung menyentuh telapak tangannya.
Hujan.
Dia kemudian menatap langit, seolah mencari celah untuk sinar matahari lewat. Namun sia-sia saja. Awan gelap telah menyelimuti langit kota sejak pagi buta. Tinggal menunggu waktu saja sampai air yang benar-benar banyak akan turun dari langit dan membuat dataran di bawahnya basah kuyup.
“Ayolah. Aku tadi menemukan buku yang bagus sekali, tapi aku tidak membawa kartu untuk meminjam. Kita masuk lagi saja, ya?” Rani setengah melonjak-lonjak di tempatnya berdiri. Dia memasukkan kedua tangan dalam-dalam kebalik saku jaket.
“Kau duluan saja, aku menyusulmu sebentar lagi.”
Rani berhenti melonjak-lonjak. Dia kemudian menuruni undakan tangga di bawah kakinya. Kemudian berdiri di samping pria tadi. “Kau sedang bad-mood, ya? Kenapa tiba-tiba sekali?”
Pria itu berpaling dan tersenyum, “Aku hanya sedang menikmati gerimis.”
Rani mencibir, “Aku tidak akan pernah bisa bersaing dengan hujan.”
“Cepatlah naik. Aku akan menyusulmu sebentar lagi.”
Rani tertawa kecil. Dia memeluk lengan pria itu sebelum kemudian setengah berlari naik dan kembali masuk ke dalam perpustakaan.
Adam menunggu beberapa saat sebelum akhirnya terus menuruni tangga dan membiarkan gerimis menyentuh tubuhnya. Dia tak merasa perlu repot-repot menyeka kacamatanya yang kini beruap dan berbintik-bintik air.
Hujan.
Ketika Adam hampir mencapai mobil, hujan deras mulai turun. Dia bisa merasakan butiran-butiran air yang lumayan besar menumbuki punggungnya, membuatnya merasa kegelian. Buru-buru dia mengeluarkan kunci dari dalam jaket, dia tidak ingin basah kuyup.
Telinganya mendengar segerombolan anak kecil berteriak-teriak kesenangan, sambil berlarian menuju teras perpustakaan. Adam memutar pandangannya, tanpa bisa ditahan dia tersenyum. Diangkatnya wajah menatap langit yang benar-benar pekat dan putih.
Adam tak lagi memaksa dirinya membuka pintu mobil. Dia memejamkan mata, mendengarkan desau angin yang bergesekan dengan ribuan partikel air yang terpelanting jatuh saling mendahului sebelum akhirnya pecah terhempas ke bumi. Atau ke atas bahunya. Di samping telinganya dia bisa mendengar riak yang tak pernah bisa dia lupakan.
Adam membuka mata.
Saat itulah dia melihatnya.
Tidak ada yang pernah membuat degup jantungnya seperti ini.
Kakinya menyeret badannya menjauhi mobil. Mendekatinya.
Wanita itu berlutut, terlihat dia menangkupkan kedua tangan kedepan mulutnya, sebuah benda kecil berwarna putih menempel erat di mulutnya, mungkin juga hidungnya. Adam memicingkan mata. Air hujan mengaburkan pandangannya.
Inhaler.
Adam tidak tahu sejak kapan air hujan yang mengalir di wajahnya bisa terasa begitu hangat. Dia juga tidak tahu kenapa sekitarnya berubah jadi pelataran parkiran.
*****
(4401)
“Aku tidak menyangka kalau kau masih menyimpan buku itu.”
Rani mengangkat wajah. “Kupikir kau ingin aku menyimpannya.”
Adam tersenyum, tapi wajahnya seperti menyesali sesuatu. Dia masih menimang-nimang buku yang diberikan Rani padanya barusan.
“Kau tahu,” Rani menelusuri pinggiran buku itu, “Aku punya beberapa bagian yang selalu aku baca berulang kali.”
“Aku minta maaf.”
“Diamlah, Adam. Perceraian kita bukan sesuatu yang perlu disesali. Aku memang tidak akan pernah sepenuhnya mengerti bagaimana bisa Ana memiliki hatimu sebanyak itu, dalam waktu sesedikit itu. Aku tidak akan menutupi rasa iriku padanya, tetapi itu adalah kenyataan yang tidak bisa kutolak. Aku juga pernah bersamamu dan bagiku itu adalah kenangan yang tidak bisa kutukar dengan apa pun.”
Adam terdiam. Dia mengerutkan kening. Rani meneruskan kalimatnya.
“Mungkin benar bahwa jodoh itu di tangan Tuhan. Kalian saling menyukai, tapi tak pernah bisa bersama. Kita pernah bersama, tapi tak lagi menyimpan rasa yang sama. Jika boleh aku memberi nasihat, hiduplah dengan berterus terang. Mungkin hatimu akan terluka lagi. Mungkin ada hati yang akan terluka lagi. Namun begitulah hidup. Aku pernah kecewa, dan aku memaafkanmu. Kuharap kita bisa meneruskan hidup masing-masing.”
Rani merapikan syal hitam yang melilit di leher dan bahunya. Dia menepuk pundak Adam pelan sebelum akhirnya membalikkan badan. Meninggalkan Adam sendirian.
***** selesai *****