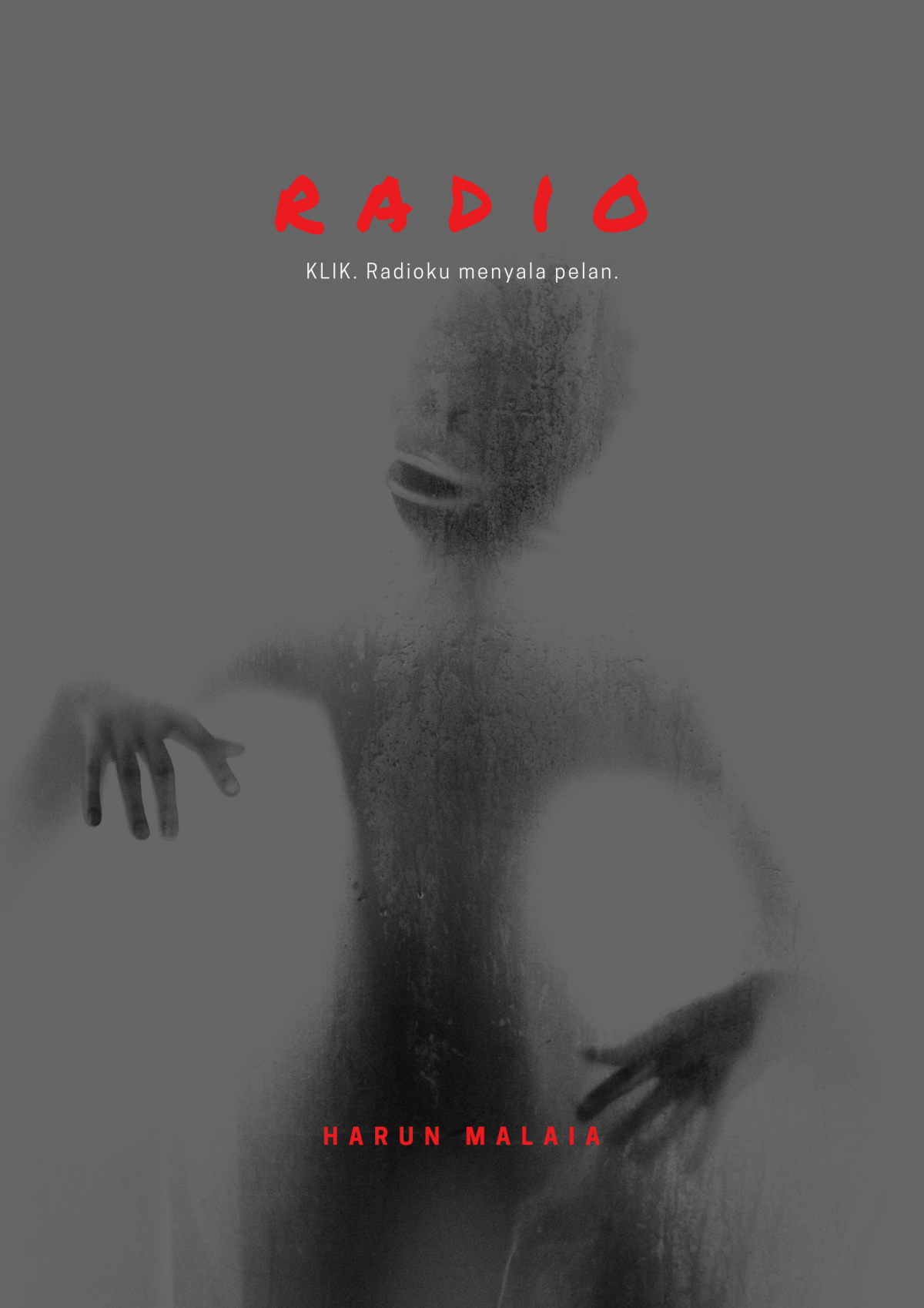LIDAHNYA hampir terbakar.
Ia tahu teh itu panas namun tak mengira sepanas itu. Buru-buru ia meletakkan gelas dan menyeka sudut bibir. Teh sialan. Makian yang kemudian segera ia sesali karena kini berarti ia tak bisa meminumnya sama sekali.
*
Sesuatu yang disumpahi akan membawa bencana. Demikian berulang ibunya katakan sambil memukul pantatnya di kamar tidur saat ia kedapatan menyentuh tubuhnya diam-diam.
Usianya tiga belas saat darah itu pertama keluar.
Roknya berwarna merah jadi ia sama sekali tak menyadari hal itu, sampai teman sebangkunya bertanya kenapa ia kencing di kelas. Pertanyaan itu dilontarkan sedikit terlalu keras karena hampir semua anak langsung melihat padanya. Terus terang ia sangat tersinggung dan reaksinya adalah ingin menangis, tetapi ia menguatkan hati dan membela diri dengan berkata ia tidak terkencing, dan dengan nada menyalahkan ia meminta temannya untuk jangan mengada-ada.
“Tapi bokongmu terlihat basah,” balas temannya bersikeras, “Coba sekarang kau berdiri,” katanya lagi.
Terang saja ia menurutinya, berdiri dengan sukarela, hanya untuk mendapati bahwa salah satu temannya yang lain sedang memotretnya dengan kamera ponsel dan tak perlu tunggu lama untuk seluruh sekolah jadinya tahu kalau ia sudah mens.
Meski sudah dihibur oleh wali kelasnya yang mengatakan ‘tidak apa-apa, mereka hanya bercanda’, ia ingat saat itu pulang dengan mata dan bokong basah.
Sesampainya di rumah, ibunya hanya memberikan tatapan dingin dan memintanya mencopot pakaian itu segera. “Air PAM sedang mengalir dan aku kebetulan sedang mencuci. Jika masih ada pakaian kotor lainnya, segera letakkan di dalam baskom di sudut dapur,” ujarnya. “Kecuali rok itu. Kau harus pisahkan karena itu darah menstruasi dan aku tak mau pakaian lain kotor karenanya,” sambung ibunya lagi sebelum lantas meninggalkannya untuk membeli softex atau semacamnya.
Ia melepas pakaian dengan malas-malasan. Beberapa kali ia pernah membaca tentang haid di buku pelajaran sekolah tapi sesungguhnya perkataan Minah tetangga sebelah yang paling diingatnya.
“Kau sudah dewasa kalau kau sudah datang bulan.”
Datang bulan. Mens. Haid. Apalah itu namanya.
“Dan kau sudah jadi wanita seutuhnya,” kata Minah lagi.
Entah apa maksudnya, ia berpikir kala itu. Jika menjadi wanita seutuhnya bermakna pulang sekolah lebih awal dengan tatapan mengolok-olok dari gerombolan anak laki-laki bau matahari dari balik pagar sekolah, rasanya tak terlalu baik.
Apalagi perutnya terasa aneh.
Bahkan seluruh tubuhnya terasa aneh.
Maka ia melepas pakaian dan menumpuknya sesuai pesan ibunya tadi.
Darah itu keluar lagi sedikit. Bercak-bercak. Dan sedikit gumpalan.
Ia menuang air dari dalam tangki biru dan mengambil kain pel.
Ibunya tak suka membersihkan lantai berulang-ulang jadi dipastikannya bercak itu tak berbekas sebelum ibunya pulang. Diulanginya sekali lagi. Sedikit terbungkuk dibereskannya ember dan kain pel, disurukkannya di sudut dapur sempit itu. Meski sudah diperas kering, tak urung sisa-sia air masih menetes dari ujung gumpalan kain pel yang sudah tak tentu arah bentuknya itu.
Setelahnya, ia menarik kursi plastik milik ibunya, duduk mencangkung di depan tumpukan baju kotor. Dalam diam ia amati baju-baju itu, jemarinya menelusuri pinggiran ember yang basah kena percikan air dari keran yang mengisi tangki biru.
Air bak kamar mandi terdengar meluap, menetes-netes di lantai. Ia bangkit dan mematikannya. Sejenak mengamati buih-buih di lantai. Diputuskannya untuk mandi.
Terdengar pintu depan terbuka dan langkah Ibunya yang tegas masuk dapur.
“Kau mau mandi?”
Ia hanya mengangguk. Menarik sehelai handuk kering kaku dari gantungan baju yang menempel miring di balik pintu.
Ia sudah akan menutup pintu kamar mandi ketika namanya dipanggil. “Tahu cara memakainya?” tanya ibunya, menyodorkan bungkusan berisi softex atau semacamnya.
Ragu-ragu ia menggeleng. Pandangannya beralih-alih antara bungkusan itu dan wajah ibunya.
“Nanti kuajarkan kalau sudah selesai. Cepatlah mandi. Aku harus segera mencuci.”
Ia mengangguk, menggigit bibir. Mendorong pintu kamar mandi yang berderit keras saat ia memaksanya merapat lebih dari seharusnya.
Bersihkan badanmu sebersih-bersihnya, terdengar suara ibunya kembali.
Ia mengangguk, meski menyadari ibunya tak lagi mengawasi. Diambilnya gayung, memutar-mutar benda itu sejenak sebelum kembali menyalakan keran. Perhatiannya sejenak teralihkan pada jentik-jentik nyamuk berwarna hitam dan kemerahan di dasar bak, mereka seperti berkelojotan tak keruan tertimpa air yang keluar dari keran. Ia menciduk beberapa. Memperhatikannya sesaat sebelum menyiramnya ke jamban leher angsa yang ada di samping bak mandi. Mati kau, bisiknya dalam hati. Sempat ia terpikir apakah jentik-jentik itu akan benar-benar mati di dalam bak penuh tahi, atau mereka justru senang, karena ia ingat pelajaran di sekolah yang mengatakan beberapa hewan senang makan tahi.
Ikan lele, misalnya. Atau ayam kampung (ia bersumpah tak akan makan ayam kampung yang pernah makan tahi, meski kemudian ia berpikir keras bagaimana cara mengetahui yang mana satu yang sudah makan tahi, dan mana yang belum sama sekali, sehingga ketika diputuskannya itu terlalu rumit akhirnya ia merevisi sumpahnya sedikit menjadi: tak akan makan segala jenis ayam kampung. Sementara untuk ikan lele ia masih pikir-pikir karena belum pernah lihat secara langsung, namun dari gambar yang ada di buku, ikan itu tidak tampak enak untuk dimakan, terdapat sungut aneh yang mengingatkannya pada ekor kecambah yang mulai busuk). Dan ia tak ingat apakah jentik nyamuk termasuk dalam daftar yang sama.
Beberapa ekor nyamuk terbang berseliweran dari dalam bak dengan bising yang nyaring, mungkin baru bertelur atau justru lepas menetas. Jadi ia memutuskan untuk menguras bak itu semuanya. Dicopotnya sumbat kayu di sudut bawah bak mandi. Benda tumpul itu tampak seperti berlumut padahal itu hanya plastik hijau bekas belanja di pasar yang dipakai untuk menyelimuti sumbat kayu agar air tak bisa merembes keluar.
Air seperti menggelegak dari lubang di bawah itu. Mengocor keras dan sekilas tampak jentik-jentik terseret ikut terbuang.
Pintu digedor keras, palang kayu yang menahannya sampai bergetar, disusul suara ibunya, “Kenapa kau kuras bak mandi itu?”
Ia buru-buru memasukkan kembali sumbat berlumut tadi. Tak terlalu rapat, tapi cukup untuk mengurangi gelegak air.
“Banyak kotorannya,” jawabnya dengan ragu. Ibunya memang tak suka jika ia membuang-buang air. “Akan kubersihkan, mumpung air mengalir,” ia menambahkan jawabannya sebelum ibunya sempat menukas.
Lalu hening. Dari luar hanya terdengar bunyi sikat beradu dengan papan penggilasan. Kadang bunyinya berlainan tergantung kain apa yang sedang dihantam di atasnya.
Ia menebak-nebak. Meski pilihannya tak banyak. Baju mereka memang tak banyak, hanya itu-itu saja. Cuci-kering-pakai-ganti. Cuci-kering-pakai-ganti.
Ia terus menebak-nebak.
Sambil menanti air dalam baknya surut.
Perutnya kembali mulas tapi bukan seperti ingin buang tahi.
Ia sampai berlutut dan meringis saat bercak darah itu keluar lagi.
Ibunya pasti mendengar tangisannya, karena sejurus kemudian ia mengetuk pintu.
“Cepatlah mandi, lepas itu kau istirahat,” katanya.
“Tapi bak air belum terisi penuh,” ia beralasan.
Ibunya terdengar tak sabar, “Tak usah kau bersihkan bak itu. Nanti kulakukan.”
Maka ia segera menyumbat ulang lubang di sudut bawah bak mandi. Sedikit kesusahan karena tangannya sedikit gemetar. Saat mengintip kembali isi bak ia dapat melihat satu-dua ekor jentik yang tak terseret keluar, mereka seperti menari-nari. Apakah mereka mengerti kalau mereka tak jadi mati?
Entahlah.
Menunggu bak air penuh ia kemudian mengambil sabun dan sampo.
Perutnya terasa aneh. Tubuhnya terasa aneh. Rasanya ingin mandi dan memakai sabun terus-terusan. Wangi lemon sintesis dari sabun di tangannya memenuhi kamar mandi sempit itu. Bercampur dengan aroma sampo yang ia tak tahu apa jenisnya. Dicobanya membaca keterangan di botol sampo tapi terlalu banyak tulisan bukan latin di sana. Jadi ia mencoba menebak-nebak saja.
Yang jelas bukan lavender. Ia ingat karena teman sebangkunya memakai parfum aroma itu, katanya banyak nyamuk di rumah dan parfum itu bisa sekalian mengusir nyamuk.
Juga bukan mawar, karena di depan rumah Minah tumbuh beberapa rumpun mawar liar, memang tak terlalu harum, tetapi ia pernah menciumnya beberapa kali dan jelas sampo di rambutnya tidak wangi seperti itu.
Malah sebenarnya campuran sabun dan samponya kini beraroma lain, seperti bau keringat di siang hari. Namun, bukan keringat menjijikkan seperti teman-temannya yang bau matahari selepas bermain bola kaki di tengah hari bolong.
Ini mengingatkannya pada aroma Mang Dana yang sering lewat di sore hari, berjualan pentol. Mungkin bukan keringat, tetapi aroma pentol. Ia tersenyum. Perutnya mulas dan terasa lapar. Mang Dana sering mangkal di rumah Minah. Katanya, Mang Dana naksir Minah, tetapi ia hanya mendengar itu dari ejekan ibu-ibu tetangga (ia sering memperhatikan ibu-ibu tetangga yang senang membeli pentol pada Mang Dana, lalu mereka berlama-lama ngobrol dan yang paling diingatnya adalah obrolan berisi ejekan dan gurauan tentang Minah dan Mang Dana).
Mang Dana tak pernah kesal meski kerap digosipkan, ia hanya tersenyum simpul lalu menyiapkan pesanan dengan cepat. Keringat yang menetes disekanya dengan handuk yang menggantung di bahu. Kadang ia memiringkan kening dan menggerakkan bahunya di sisi yang sama.
Lengannya gesit memilah-milah. Satu tusuk. Dua biji. Kuah. Goreng. Kembalian dua ribu. Pesanan berapa bungkus. Kuah pedas. Tidak pedas.
Bungkus. Makan di tempat.
Keringat. Handuk. Bahu. Kening. Lengan.
Lengan Mang Dana kecokelatan terbakar matahari (ia tahu itu terbakar karena dari balik lengan kaos putihnya yang longgar ia bisa melihat kulit lengan atas yang jauh lebih cerah), tetapi aromanya tidak sama dengan leher-leher legam teman sekelasnya yang main bola di siang bolong. Lengan Mang Dana ramping dan dari samping terlihat jelas lekukan garis yang memanjang hingga siku. Ia ingat betul karena ia sering duduk di depan rumah Minah—tidak mesti belanja pentol. Kadang hanya duduk-duduk, dan melihat-lihat. Anak kecil tidak masalah kalau melihat-lihat.
Mang Dana beberapa kali memberinya pentol gratis. Sambil tersenyum ia akan memisahkan sebatang pentol dan menyiramnya dengan saus kacang pedas yang lengket. Biasanya itu akan diberikannya kalau pembeli lain sudah selesai ia layani. Mang Dana kemudian akan duduk di pagar teras, mengobrol dengan Minah.
Ia senang diberi pentol gratis, karena selain ia tak perlu bayar (ibunya tak senang ia jajan—atau memang tidak punya uang untuk memberinya jajan, entahlah), sambil makan pentol gratis, ia bisa melihat Mang Dana lebih dekat. Kalau diperhatikan baik-baik, di pergelangan tangannya lebih banyak rambut-rambut halus yang menipis hingga ke bagian pangkal jari kelingkingnya.
Ia dapat melihatnya dengan jelas karena kini aroma sampo dan sabun yang menyelimuti tubuh dan kamar mandi sempit itu seperti membawa gerobak Mang Dana ke dalam kamar mandi.
Pesan satu Mang. Pesan tiga Mang. Ibu-ibu mulai berdatangan.
Namun, yang membuatnya tersipu, Mang Dana justru kembali menyiapkan sebatang pentol untuknya. Lengkap dengan kuah saus yang melimpah. Lengan Mang Dana terjulur padanya, ia dapat melihatnya jelas. Rambut-rambut di lengannya. Beserta aroma keringat dan pentol yang berkuah kental lengket.
Untuk pertama kali napasnya tersengal dan mulas yang dirasakannya seakan tak berujung. Membuat jari-jari kakinya tertarik. Punggungnya melengkung menahan pegal yang tertahan. Kepalanya terasa berat dan ringan secara bersamaan.
Lebih banyak sabun ia pakai.
Kemudian ibunya datang dan ikut memesan pentol pada Mang Dana. Hanya wajahnya terlihat tak senang. Ibunya menggedor-gedor gerobak pentol Mang Dana.
“Apa yang sedang kau lakukan?”
Pintu kamar mandi digedor kencang. Saking kuatnya, penyangganya yang hanya sepotong balok kecil yang dipaku longgar jadi terbuka. Tentu saja ibunya melihat semuanya.
Tanpa bicara ibunya menyiramkan air bak mandi banyak-banyak.
Menyapu bersih sabun dan sampo yang sedang ia pakai.
Menyiram keluar aroma keringat dan pentol Mang Dana.
“Pakai handuk dan tunggu di kamar,” perintah ibunya.
Ia tak membantah, berlalu, dan menunggu. Hanya tahu kalau ia sudah melakukan kesalahan karena saat masuk ke kamar tidur, ibunya membawa sebilah penggaris yang sejurus kemudian mendarat tipis di bahunya.
“Jangan pernah ulangi hal itu,” gumam ibunya dingin, tangannya bergerilya.
Kembali penggaris itu melekat di kulitnya.
Saat wanita itu keluar kamar ia bisa mendengar kalau ibunya menyumpahinya. Anak sialan.
Matanya memanas. Hatinya terbakar.
*
Anak sialan.
Ia memainkan jari di atas pinggiran gelas. Masih panas.
Tak ingin bibirnya terbakar lagi, ia menunda minumnya.
Sesuatu yang ditahan lama-lama akan jadi penyakit. Kalau tidak sakit badan. Sakit hati. Minah pernah mengatakan hal itu padanya. Saat itu ia sedang duduk-duduk di depan terasnya. Mereka sedang menunggu Mang Dana (meski tentu Minah tak pernah tahu tentang perasaannya sendiri pada penjual cilok itu).
Dan ia juga masih anak sekolah.
“Kapan kau tamat?” tanya Minah malas-malasan.
Ia menjawab dengan nada serupa. Mereka sedang malas bicara. Laki-laki yang ditunggu tak kunjung kelihatan batang hidungnya.
Kadang hidup memang begitu.
Pernah sekali waktu, hujan deras sampai tak bisa melihat langit. Ia sedang menggeser deretan pot kaktus di depan terasnya sendiri agar tidak tempias. Lalu di ujung lorong, dilihatnya gerobak itu.
Senyumnya terbit dan ia buru-buru mematut dirinya pada kaca gelap di jendela.
Mang Dana berhenti seperti biasa.
Namun, sore itu, mungkin karena melihat teras Minah sedang kosong, pria itu justru menuju terasnya. Ia ingat betapa keras jantungnya memukul dada. Senyum yang tadi terbit segera hilang berganti dengan butir-butir keringat yang menghiasi kening.
“Saya numpang berteduh, ya.”
Ia kehilangan kata. Terangguk bagai pungguk. Lalu ia buru-buru berlari ke dalam. Ibunya menanyai siapa yang datang. Ia mengatakan hanya Mang Dana. Mungkin menyadari hujan deras yang sepertinya tak kunjung reda, ibunya menyuruhnya membuatkan segelas teh panas.
Ia menurutinya.
Itu pertama kali ia membuatkan minuman untuk seorang pria.
Tangannya gemetar luar biasa, hampir saja ia menumpahkannya.
“Terima kasih.”
Ia masih tak mampu bicara. Meski kini debaran di dadanya sudah tak lagi sama. Berganti dengan gelenyar hangat yang membuat napasnya sesak dan perutnya teraduk-aduk.
Ia memilih permisi untuk duduk di dalam, menarik kursi mendekat di balik jendela. Bisa dilihatnya Mang Dana tersenyum padanya.
Senyumnya kembali datang bertandang.
Jadi begini rasanya, bisiknya dalam hati. Jemarinya menyusuri terali yang memagari, batas antara dirinya dan Mang Dana.
Menyaksikan semuanya.
Mang Dana duduk dalam diam, menyesap isi gelasnya.
Gelas diangkat sebatas dada. Kepulan uap panas mengudara, menghilang di matanya.
Gelas mendekat pada bibirnya. Memberinya sentuhan panas.
Satu tegukan.
Melewati jakun itu. Leher dengan bintik-bintik tunas rambut yang bernas.
Setelah itu ia menurunkan pandangannya ke pangkuannya sendiri. Memainkan kuku ibu jarinya, mengupas sisi-sisi yang tak rata. Menghilangkan sesuatu yang entah apa itu.
Saat ia kembali mengangkat kepala, Mang Dana sedang melihatnya.
Langkahnya ringan saat mendekati pintu. “Bisa minjam handuk, Dik?”
Ia terdiam sesaat di kursinya. Untuk kemudian melangkah tanpa suara. Semua terasa melayang. Seakan di awang-awang. Diambilnya handuk kecil yang terlipat kaku di dalam lemari miliknya. Mengangsurkannya dengan ragu-ragu.
“Saya pinjam dulu. Punya saya basah,” jelas Mang Dana, “Besok saya kembalikan.”
Ia tidur memeluk handuk itu selama berminggu-minggu.
Sampai hari itu datang. Usianya tujuh belas tahun menjelang.
Ibunya minggat, bersama Mang Dana.
Ia sebenarnya tak pernah tahu apakah ibunya benar-benar pergi. Serta apakah benar memang Mang Dana yang membawanya lari.
Hari itu ia pulang sekolah sehabis ujian dan mendapati rumah kosong. Bukan hal luar biasa. Ibunya memang kerap pergi sampai senja hari, sebagai buruh cuci, ia berpindah-pindah dari rumah ke rumah, tergantung siapa yang menghubunginya lebih dulu (ibunya harus pergi sedikit jauh karena di sekitar rumahnya, mereka semua mencuci sendiri dan beberapa sudah memakai mesin cuci). Maka ia masuk dengan kunci cadangan yang biasa diselipkan di bawah pot-pot kaktus di sudut teras.
Malam larut menjelang, tetapi ibunya tak juga kunjung pulang.
Barulah ia mulai bimbang.
Pada Minah ia bertanya, “Apakah kau melihat ibuku seharian ini? Atau mungkin ia meninggalkan pesan saat pergi?”
Minah hanya bilang kalau ibunya terlihat keluar rumah sejak pagi dengan raut wajah berseri-seri.
Ia tak punya ponsel untuk menghubungi ibunya. Maka ia meminjam pada Minah.
“Nomornya tak aktif,” ujar Minah.
Ia kemudian mengorek-ngorek laci, mencoba mencari nomor ayahnya yang sudah tujuh tahun tidak pulang dari Kalimantan.
“Nomornya tidak bisa dihubungi,” kata Minah lagi.
Malam itu ia tidur di ruang tamu, terkantuk-kantuk menunggui pintu. Ia memang tak dekat dengan ibunya, tetapi tak sedikit pun terlintas dalam pikirannya kalau wanita itu akan pergi meninggalkannya seorang diri. Pikiran-pikiran buruk lainnya yang justru menghantui benaknya saat itu. Bagaimana jika saat mencuci ibunya jatuh sakit? Bagaimana jika ternyata ia mengalami kecelakaan? Ia sering melihat kecelakaan di jalan raya saat pergi-pulang sekolah. Suatu kali misalnya, ia melihat seorang pengendara motor jatuh dengan helm terbelah. Ia tak berani melihat terlalu dekat. Setiap ada kecelakaan ia akan pergi menjauh. Mempercepat langkah, mengubah arah. Maka ia tetap menitip pesan pada Minah, sekiranya ada yang menghubungi.
Subuh pun datang, tetapi tetap tak ada tanda-tanda siapa pun akan bertandang. Diberanikannya masuk ke kamar ibunya yang terkunci. Ia tahu kuncinya ada di selasar lubang angin di atasnya. Berjingkat ia merabai debu-debu yang menempel di sana.
Ada.
Pintu kamar terbuka.
Seberkas sinar jingga mengintip dari tepi daun jendela yang rapat terkunci.
Sunyi pelan-pelan pecah oleh kumandang ayat-ayat dari musala di ujung lorong.
Ia merapatkan pintu kamar. Meratakan punggung di sana. Menelaah seisi kamar sempit itu. Di salah satu sudut, di atas dipan, kasur tipis ibunya tergulung rapi tak berpenghuni. Beberapa helai pakaian terlihat menumpuk, berantakan di atasnya. Ia menajamkan mata, setengah berharap ibunya tersuruk di sudut sana.
Tentu saja sia-sia.
Beringsut, ia menarik langkah mendekati dipan kayu sempit itu. Pikiran kalau ia benar-benar tinggal sendiri mulai merasuki. Berhati-hati, diangkatnya pakaian dan selimut dari sana, membongkar kasur tipis bergelung tadi. Meringkuk, ia duduk di pinggiran tempat tidur itu, gigil ia tersedu, lalu punggungnya menyerah. Seperti bayi, ia tidur menyamping, pandangannya mengabur. Dingin segera memeluk.
Matahari sudah tinggi saat ia terbangun. Sudut-sudut matanya terasa lengket dan berpasir.
Kali ini semangatnya lebih menyala. Menyeka hidung yang setengah buntu, ia bangkit dan menuju sudut kamar di seberangnya. Dibukanya lemari yang dulu sering ia jadikan tempat sembunyi. Dulu. Dulu sekali.
Tanpa sadar air matanya kembali tumpah melimpah. Lututnya goyah. Di depan lemari dengan kaca abu-abu itu ia tersimpuh, memandangi beberapa helai daster koyak-koyak yang tergantung di dalam sana. Ia bisa mencium aroma sabun yang dipakai Ibunya.
Dijulurkannya tangan, menggapai ujung-ujung kain yang terasa kasar. Bisa terdengar derap sikat menempa papan penggilasan. Lalu air membilasnya.
Sikat. Bilas.
Sikat.
Bilas.
Air yang banyak membilas busa-busa sabun yang kemudian beriringan menuju lubang di sudut rumah.
Hanya kini yang tersisa adalah air matanya.
Ia bahkan tak benar-benar paham kenapa menangis. Perasaannya jadi tiba-tiba sangat sedih. Bahkan jauh sebelum ia benar-benar yakin kalau ibunya telah pergi dan mungkin tak akan pernah kembali.
Perihal apakah Mang Dana yang membawanya, dihembuskan oleh para tetangga. Karena memang semenjak hari itu, tak pernah lagi gerobak pentol itu mangkal di situ. Bisa diduga, Minah juga kini memasang wajah masam padanya. Tak lagi membuka pintu meski ia mengetuk berkali-kali.
Mang Dana sialan.
Ia memutuskan untuk tak lagi pergi ke sekolah, hingga kemudian di suatu petang, wali kelasnya datang. “Kami baru mendengar berita tentang ibumu,” ujarnya.
Ia tak tahu harus menjawab apa.
“Masuklah lagi, tinggal satu semester maka kau akan lulus.”
Ia menggeleng. Sekolah tak ada lagi dalam pikiran.
Mereka sama-sama tahu kalau ia tak punya uang. Selama beberapa hari ini ia menerima sumbangan tetangga, tetapi itu tak banyak. Akan segera habis.
Ia sudah terpikir untuk membantu dari pintu ke pintu. Ia tahu kalau ia bisa dapat beberapa ribu dari menyetrika beberapa helai pakaian. Atau mencuci pakaian seperti yang biasa ibunya lakukan.
“Selesaikan sekolahmu, lebih mudah kau cari kerja nantinya,” wali kelasnya itu berkata, seakan bisa membaca pikirannya.
Ditimbang-timbangnya beberapa saat. Ia kemudian mengangguk.
Tangisnya pecah saat kemudian wali kelasnya memberi amplop. Sumbangan dari teman-teman, katanya.
“Jumlahnya memang tak seberapa, tapi kau harus sekolah lagi.”
Hari Minggu besoknya ia membentangkan tikar di teras sempit rumahnya. Pada Minah ia minta tolong untuk menyebarkan kabar, bahwa ia menjual baju-baju bekas, serta apapun barang layak jual di rumahnya yang tak lagi ia perlukan. Meski terlihat enggan, Minah membantunya. Saat petang menjelang, terasnya kosong dan mereka berhasil mengumpulkan beberapa ratus ribu.
Selanjutnya, ia hidup dari hari ke hari. Kadang saat bekerja sambilan, ia lebih memilih makanan sebagai bayaran karena itu jauh lebih menyenangkan. Tak harus mencuci piring. Tak harus masuk dapur, memikirkan kompor, dan segala pecah belah tak menarik yang ada di sana.
Karena hal-hal itu beberapa kali membuatnya terkenang ibunya.
Ia tak paham bagaimana cara perempuan itu membuat mereka bertahan selama ini. Yang jelas, tidak mungkin ayahnya yang mengirimi mereka uang, karena ia sendiri tak pernah dapat kabar sedikit pun dari laki-laki itu, bahkan setelah berbulan-bulan ibunya minggat.
Sedikit demi sedikit ia memahami beban ibunya.
Maka ia mulai belajar memaafkan. Tak lagi membawa hawa benci di hatinya.
Ia bahkan beberapa kali sengaja duduk di dapur sempit Ibunya. Mencoba mengenang langkah-langkahnya yang tegas. Serta bibirnya yang selalu penuh gumaman.
Air matanya menetes.
Perlahan diambilnya gelas teh yang tadi diseduhnya. Menyentuh pinggirannya.
Minuman sialan. Namun, kali ini bibirnya tersenyum.
Lidahnya tak lagi terbakar.
Teh itu telah dingin dengan sendirinya.
***selesai***