Fly me to the moon, and let me play among the stars…
Let me see what spring is like on Jupiter and Mars…
In other words, hold my hand.
In other words, darling, kiss me…
*
Sayup-sayup terdengar Julie London dari speaker yang kau pasang; selain suaranya yang merayu, tak ada yang bicara. Sudah hampir lima menit kau duduk bersamanya, namun tak sepatah pun kata terucap. Hingga akhirnya kau buka suara, “Kudengar kau tak rutin meminum obat.”
Kau lihat dia mengangkat mata. Pandangan kalian bertemu.
“Lalu kau juga masih….“ Sejenak kau diam, mencari kata yang pas.
“Melacur.”
Berdeham kecil, perempuan itu yang menyelesaikannya. Kau melihatnya merogoh isi Prada tiruan di pangkuannya. Mengeluarkan lipstik dan mulai memoles bibir, tangannya yang lain memajang kaca kecil. Kau yakin benar keduanya gemetar. Di balik lengan baju panjangnya, kau tahu semua tak baik-baik saja.
Ketika mendapatkan panggilan darinya tadi pagi buta, kau sudah menduga ada yang tak beres dengannya; yang tak kau tahu, apa dan bagaimana.
“Bisakah aku mampir besok sore? Ada yang ingin kupastikan.”
Kau ingat bahkan sempat terdiam beberapa saat, mencoba mencerna dan meyakinkan bahwa benar dia yang menelepon.
“Kau di mana? Apa kau baik-baik saja?”
Gemerisik di telepon bercampur dengan desah napasnya. Kau mendengarnya terbatuk. Suaranya sedikit sengau. “Mungkin jam lima. Atau jam enam. Kau masih bisa menunggu?”
Kau tak bisa tertidur sepicing pun setelah menutup telepon. Sudah sekian lama sejak terakhir kali kau dan dia bicara.
Dan sekarang, di sini kalian berdua.
Kembar tapi tak serupa.
Meski tentu saja kau masih bisa melihat kilasan masa lalu dan masa depanmu pada wajahnya. Kau melihatnya mematut bibirnya yang penuh, merah kontras dengan wajahnya yang pucat. Kau kembali buka suara, “Tindakanmu itu sungguh berbahaya. Tidak hanya kau memperburuk status penyakitmu, namun kau juga berisiko menularkannya.”
Dengan bunyi ‘klik’ yang jelas dia menangkupkan cermin. Matanya terangkat padamu. “Kau tahu aku tak peduli.”
“Tapi aku peduli.”
Tak kau sangka dia terbahak keras sekali, menepuk lutut, dan memegangi perut. Tawanya berubah jadi sengal napas yang memburu.
“Ooh…” ujarnya sambil mengeringkan sudut mata, “setelah sekian lama, tak kusangka kau masih lucu saja, Ariana.”
Rautmu sontak mengeras. “Aku bisa mengirimmu pada psikiater.”
“Lakukan apa yang kau mau. Aku juga begitu.”
Kau menggeleng gusar. “Luana, kita bukan anak kecil lagi.”
“Terang saja bukan anak kecil. Kau pikir pelangganku buta? Atau pedofil? Mereka hanya mencari selangkanganku! Setan! Kau seharusnya bersyukur aku memberikan virus kematian pada mereka dengan cuma-cuma!”
Menahan amarah, kau buka lembar dokumen di depanmu. Mencoba memusatkan perhatian pada catatan yang sudah kau pelajari sejak pagi.
Setidaknya dia kini tak lagi membisu, begitu pikirmu.
“Tercatat positif HIV sejak lima tahun lalu. Sempat menerima obat rutin. Namun belakangan tak lagi melakukannya.” Kau dorong dokumen tersebut padanya, menuntut penjelasan. “Apa yang terjadi? Kenapa berhenti berusaha? Lalu apa yang membawamu periksa hari ini?”
Kau melihatnya mengangkat bahu, mendesah malas. Kembali mengorek isi tas, dia mengeluarkan sebatang rokok dan pemantik.
“Luana! Kau tak boleh merokok di sini!” suaramu meninggi.
“Tak ada tanda larangan.”
“Demi Tuhan! Jika kau begini tak peduli, apa gunanya hidup?!”
Kini kau saksikan dia menurunkan rokok, memutar bola mata. “Kau terlalu lurus, Ariana. Wajar para pria takut padamu. Santailah sedikit. Papa Mama pasti menangis dalam kubur kalau tahu anak kesayangannya jadi perawan tua.” Mendengar nada suaranya mencela, wajahmu panas membara.
“Air mata mereka sudah habis karenamu.”
Dapat kau lihat perkataanmu melukainya. Luana menyilangkan tangan di depan dada, bibirnya bergetar saat berujar, “Kalau perlu mereka menangis darah karena garis keturunan Gouw akan habis di tangan kita: perempuan celaka.”
Kau terkesiap, tak siap.
“Oh, kau pikir aku tak tahu tentang operasi kanker rahimmu, Ariana?” Kembali, dia menyulut rokok. Kali ini kau tak menghentikannya.
Tangannya bergetar. Api berkobar. “I’m sorry for your loss.”
“Katakan apa maumu, Luana.” Setengah mati kau menahan air mata.
Jelas kau sadari dia tak peduli perasaanmu, karena seraya mengumpulkan segenap rambutnya ke bahu kiri, dia lanjut bicara, “Aku periksa karena badanku tak seperti biasa. Belum pernah aku selelah ini. Sekacau ini.” Untuk pertama kali kau mendengar kegelisahan dalam suaranya. Begitu juga dengan caranya mengukur diri dengan merentangkan kedua tangan di depan tubuhnya, seakan mengukur dan menghitung semua kesalahan yang ada di sana. “Jika benar akan segera mati, aku ingin memastikannya. Setidaknya kau bisa mengurusi mayatku nanti. Kau mau mengurusi mayatku, kan?”
Kau tak menjawabnya. Bimbang apakah dia sedang kembali memancing amarahmu atau bicara sejujurnya.
Lama kalian bertatapan.
Sampai akhirnya pintu ruangan diketuk. Seorang perawat masuk membawa hasil laboratorium sore ini. Berterima kasih, kau menunggunya benar-benar pergi lalu membuka amplop tersebut.
Dari ekor matamu kau menangkap Luana bangkit dari kursinya. Berjalan berkeliling, mengamati acuh tak acuh pada piagam-piagam pelatihan dan penghargaan di dinding. Saat kembali bersuara, dia bertanya, “Bagaimana kondisiku?”
Kau hampir menyergah ‘apa pedulimu?’ namun tak jadi. Alih-alih, kau bergumam, “Tak terlalu bagus. Namun kurasa kau justru bahagia.”
Lembaran kedua.
Jantungmu mencelos.
Mengangkat wajah, suaramu bergetar saat berkata, “Kau harus kembali meneruskan terapi.”
Kau melihatnya menggeleng. “Kau yang bilang apa gunanya hidup jika tak peduli. Aku ingin mati.”
Dadamu panas, kau sodorkan hasil laboratorium padanya.
“Bacalah. Aku tak tahu caranya agar kau bisa peduli, tapi Tuhan mengerti. Mungkin ini kerja rahasianya.”
Nanar, kau lihat matanya melebar. Bibirnya gemetar, “Aku…,” dia tak sanggup menyelesaikan kalimatnya.
Kau membantunya, “Ya. Kau sedang berbadan dua.”
Hening.
Tak kau dengar Luana membalas ucapanmu.
Justru kau saksikan dia memberesi tas di meja dengan tergesa. Sebelum menjangkau pintu keluar dia berhenti sejenak dan membalikkan badan. Kau lihat matanya berkaca-kaca. “Kurasa aku butuh udara segar. Keluar sebentar. Pikiranku…” dia memegang kepalanya sambil terisak, menangkup wajah, “maaf karena telah berkata buruk padamu.”
Sejurus kemudian dia berlalu.
Sayup-sayup hanya Julie London yang masih mengalun di telingamu.
*
Now you say you’re sorry
For being so untrue
Well, you can cry me a river, cry me a river
I cried a river over you…
*****
*Apatia (Spanish) adalah kondisi kurangnya antusiasme, motivasi, ataupun kegembiraan. Merupakan istilah psikologi untuk kondisi ketidakpedulian, di mana individu tersebut tidak merespon baik secara emosi, sosial, atau aktivitas fisik.




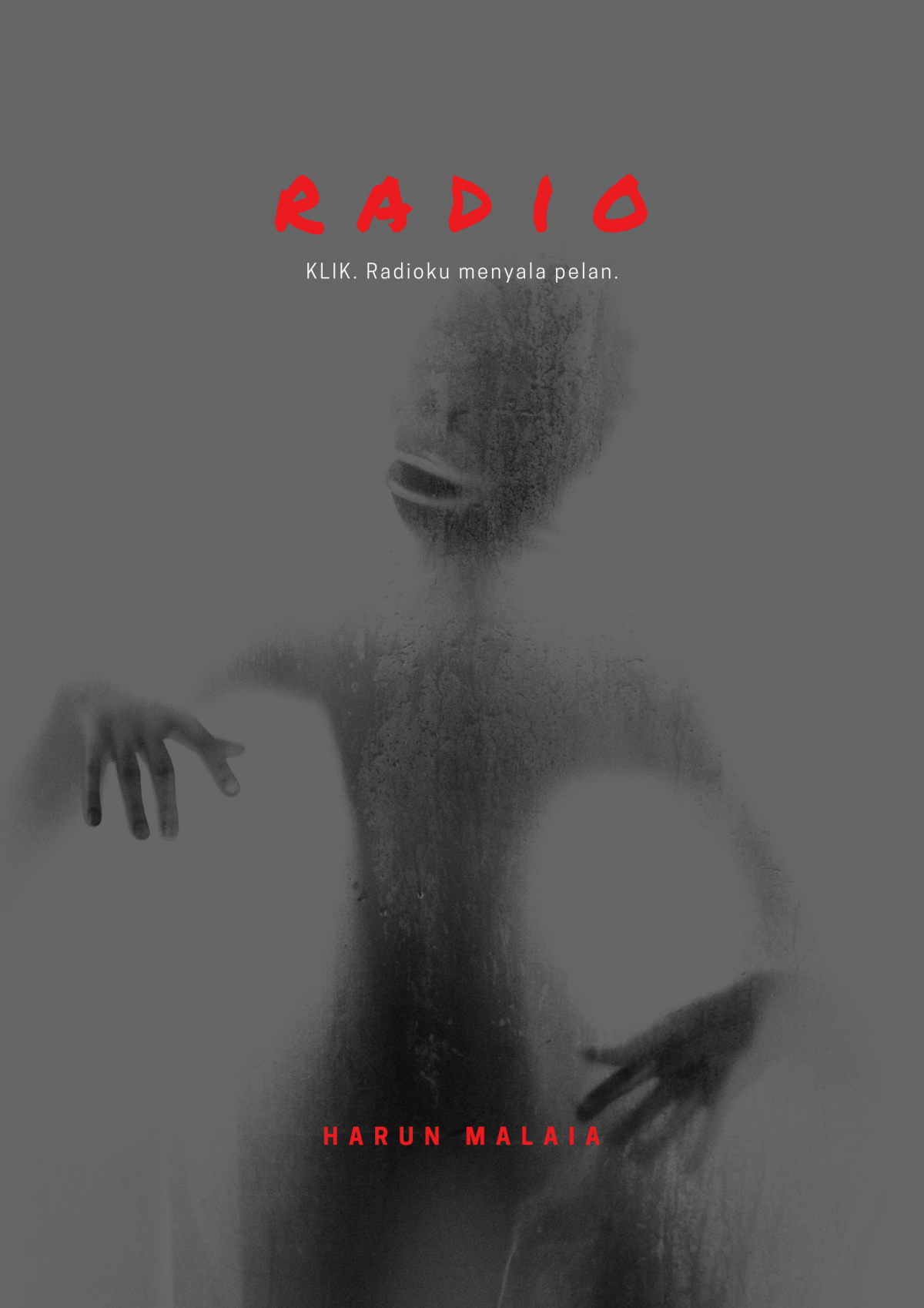


Tinggalkan Balasan