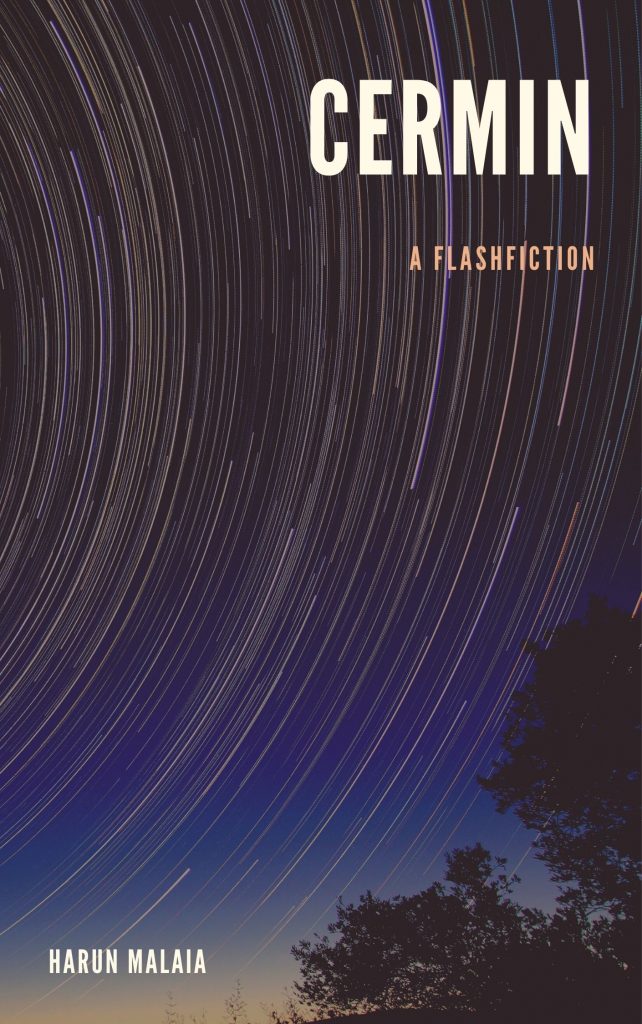Tag: harun malaia
-
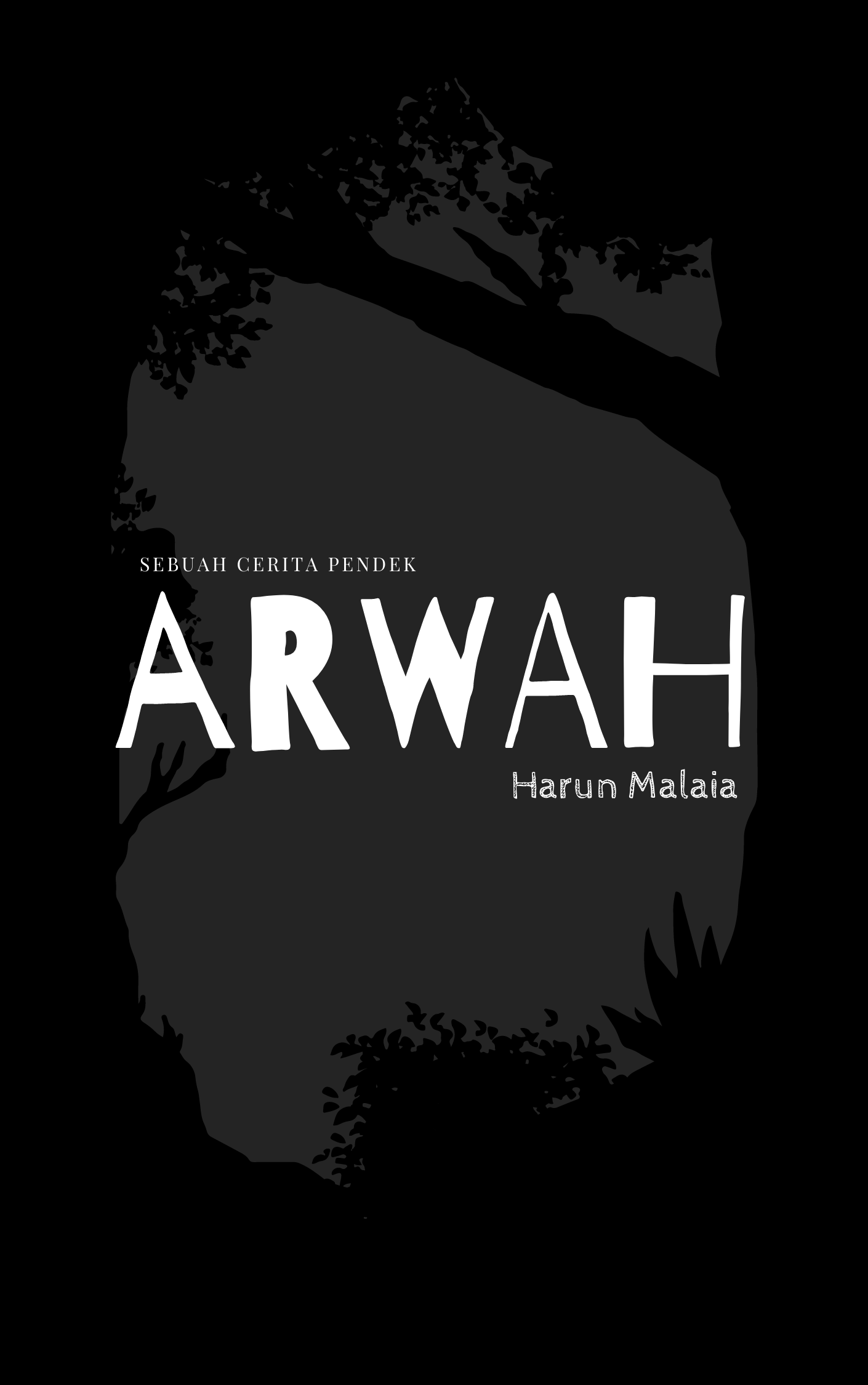
Kurang lebih sejak tiga bulan yang lalu, arwah istri saya datang berkunjung ke rumah. Saya mengenalinya karena dia mengenakan pakaian kesukaannya. Terusan warna krem yang jatuh tepat di bawah lutut, bermotif bunga bakung. Entah dari mana dia mendapatkannya, seingat saya semua pakaiannya sudah saya sumbangkan karena saya tidak sanggup mengenang kepergiannya yang begitu tiba-tiba. Awalnya,…
-
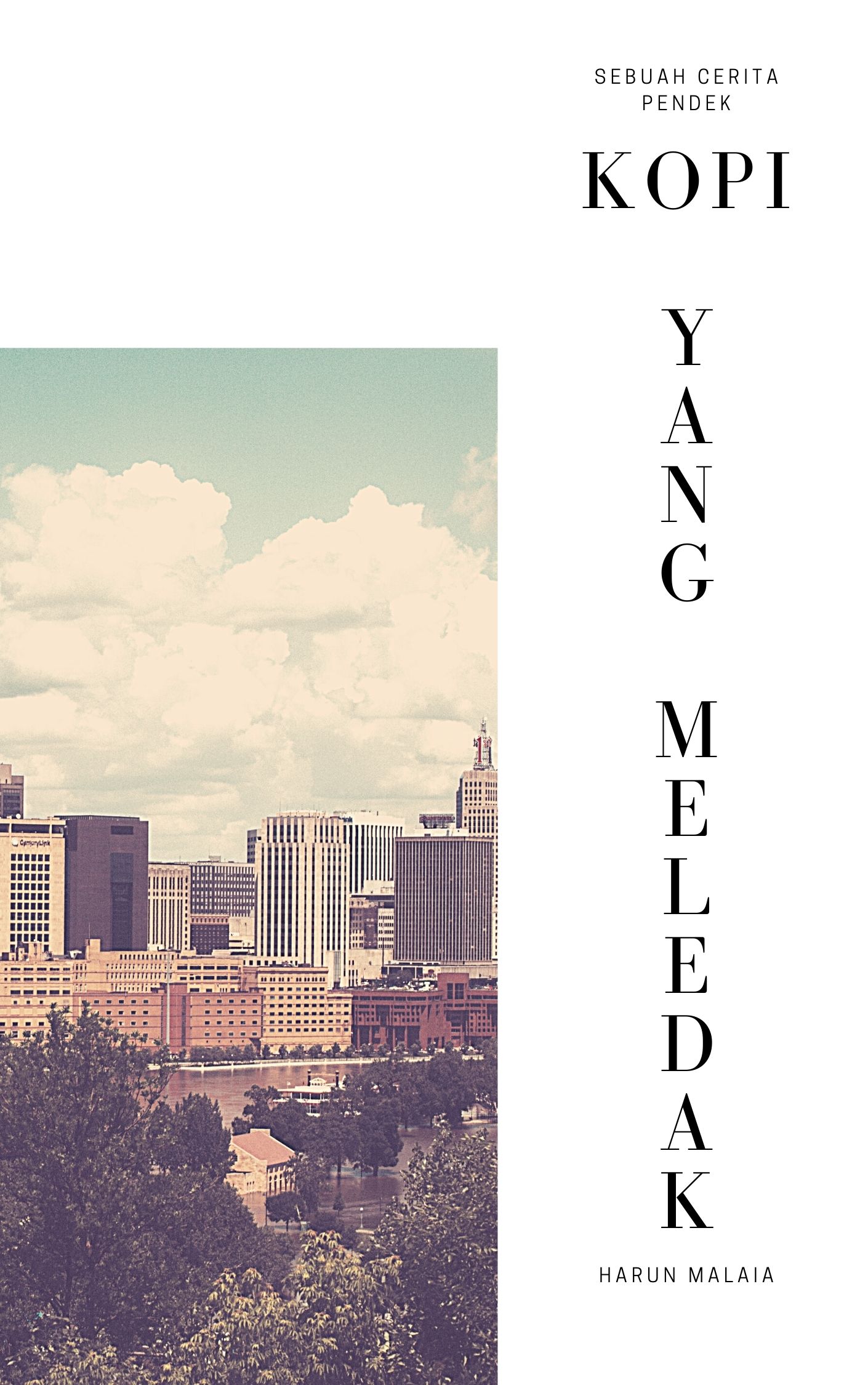
Bagi mayat-mayat hidup itu, waktu minum kopi adalah kebahagiaan yang tak terganti. Untuk sesaat yang tak lama, mereka akan kembali merasakan jadi manusia. Dua kali sehari: jam tujuh pagi, dan sore saat matahari hampir terbenam. Masing-masing dua jam. Itu adalah waktu yang diizinkan untuk minum kopi. Meski sebenarnya mereka ingin minum lebih banyak dari itu,…
-

Dengan debaran dada yang makin kencang, kau seret langkahmu mendekati salah satu toko dengan tulisan besar menyala di persimpangan jalan itu. TOKO KUDA PONY—huruf Y-nya sudah terbalik, kemungkinan lepas paku bagian atasnya. Bangunan di samping kanan-kirinya tampak gelap, membuat toko itu semakin mencolok. Beberapa puluh langkah sebelum sampai di sana, kau berhenti. Menimbang-nimbang. Menajamkan pandangan. …
-

“Apa kabarmu?” Ia mengerling, mengangkat bahu. Aku mengangguk paham, tak ada jawaban ‘baik’ bagi pesakitan, kecuali saat mereka dibebaskan. “Aku membawakan bacaan,” kudorong bingkisan di atas meja. Kulihat ia mengerling malas di kursinya, jelas tak berminat berbincang. “Ibu bilang kalau lagi-lagi kau tak membalas suratnya, ia akan datang sendiri.” Kali ini ia mengangkat wajah, sejajar…